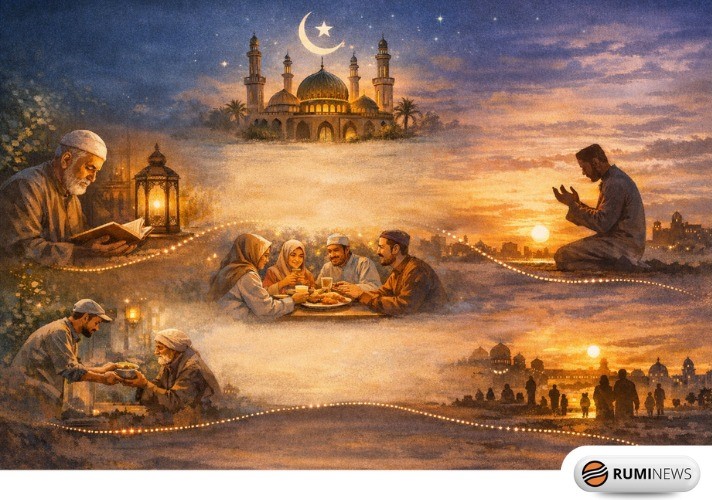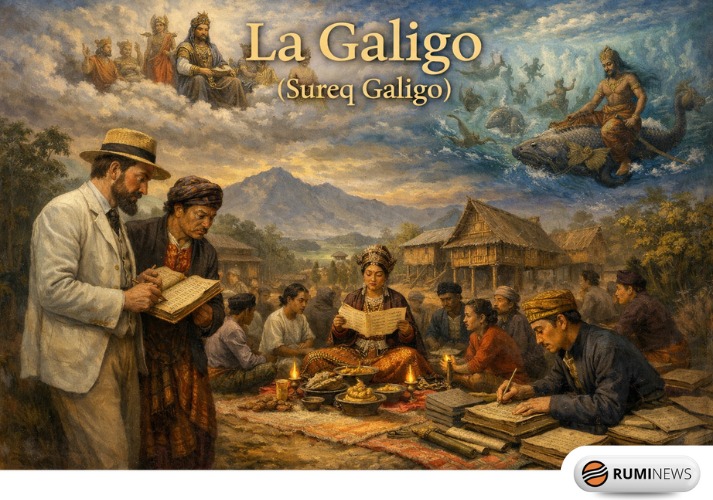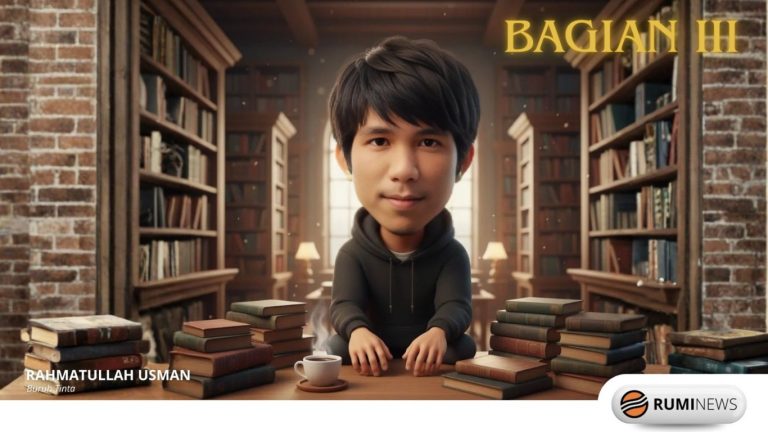ruminews.id – Ketika bangsa ini kembali menatap tanggal 28 Oktober—hari di mana para pemuda bersumpah setia pada satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa—kita diingatkan pada amanah konstitusi yang tak kalah fundamental: Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal ini bukan sekadar susunan kalimat hukum, melainkan janji sosial bahwa kekayaan alam Indonesia harus dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Dalam konteks itulah sosok Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), menjalankan tugas berat. Di bawah kepemimpinannya, Kementerian ESDM menggerakkan program hilirisasi, memperluas akses energi hingga ke pelosok, membuka kesempatan bagi koperasi, UMKM, dan organisasi keagamaan untuk ikut mengelola tambang, serta memastikan sumber daya alam tidak hanya menjadi komoditas bagi segelintir elite, melainkan tumpuan hidup rakyat banyak.
Langkah-langkah itu adalah upaya nyata untuk menghidupkan kembali semangat Pasal 33: negara sebagai pengelola dan penjaga keadilan ekonomi. Ketika energi menjadi terang bagi desa-desa, ketika tambang membawa kemaslahatan bagi masyarakat sekitar, dan ketika keuntungan sumber daya dirasakan lintas wilayah, maka konstitusi bukan lagi teks, melainkan kenyataan.
Namun, di tengah kerja besar itu, Bahlil menghadapi sisi gelap bangsa ini yang belum sepenuhnya kita taklukkan: rasisme.
Rasisme, Luka yang Masih Menganga
Rasisme di Indonesia sering kali muncul dalam bentuk halus—candaan, stereotip, atau komentar bernada merendahkan. Namun dalam kasus Bahlil, serangan itu tampil telanjang: hinaan terhadap warna kulit, asal daerah, bahkan latar sosial. Ia menjadi sasaran ujaran kebencian yang menodai martabat kemanusiaan dan menyinggung nurani bangsa.
Ironisnya, peristiwa itu terjadi di tengah upaya pemerintah menegakkan amanah konstitusi dan mewujudkan keadilan sosial. Hinaan semacam itu bukan hanya menyakiti seorang menteri, melainkan mencederai cita-cita Sumpah Pemuda—bahwa kita satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air.
Bahlil merespons dengan ketenangan. Ia tidak membalas, tidak melapor dengan amarah, tetapi memaafkan. “Saya biasa dihina sejak kecil, saya bukan anak pejabat,” katanya. Sikap ini menunjukkan kualitas seorang pemimpin yang matang: tegas dalam kebijakan, lembut dalam hati. Di tengah derasnya gelombang kebencian di ruang publik, sikap memaafkan justru menjadi bentuk tertinggi dari kekuatan moral.
Rasisme bukan hanya persoalan personal; ia cermin dari kegagalan kolektif kita memahami makna kebangsaan. Bila seorang putra bangsa yang memegang amanah publik masih diserang karena identitasnya, maka kita sedang mundur dari nilai yang diperjuangkan pemuda 1928.
Sumpah Pemuda dan Panggilan Moral Bangsa
Menjelang peringatan Sumpah Pemuda ke-97, bangsa ini dituntut untuk tidak hanya menghafal teks sejarah, tetapi juga menghidupkan maknanya. Sumpah Pemuda bukan sekadar momentum seremonial, melainkan kompas moral yang mengingatkan bahwa persatuan Indonesia tidak lahir dari keseragaman, melainkan dari keberagaman yang saling menghormati.
Kita harus berani menolak ujaran kebencian, menghapus diskriminasi rasial dari ruang publik, dan memastikan setiap kebijakan negara berpihak pada rakyat tanpa memandang asal-usul. Pendidikan multikultural di sekolah, etika digital di dunia maya, dan keteladanan pemimpin menjadi fondasi baru bagi persatuan nasional.
Bahlil Lahadalia menjadi simbol dari dua ujian besar bangsa ini: bagaimana mengelola kekayaan alam dengan adil sekaligus menjaga kemanusiaan dari luka rasisme. Dari dirinya kita belajar bahwa tugas seorang pemimpin bukan hanya membangun infrastruktur, tetapi juga membangun karakter bangsa. Ia menunjukkan bahwa kemajuan ekonomi tanpa kematangan moral akan kehilangan maknanya.
Menjelang 28 Oktober, marilah kita refleksikan ulang arti persatuan. Persatuan tidak berarti tanpa perbedaan, dan perbedaan tidak boleh melahirkan kebencian. Ketika rasisme telah kita singkirkan, dan ketika amanah Pasal 33 benar-benar dijalankan untuk kesejahteraan rakyat, maka janji para pemuda 1928 akan kembali hidup di antara kita—bukan sekadar dalam pidato, tetapi dalam tindakan.