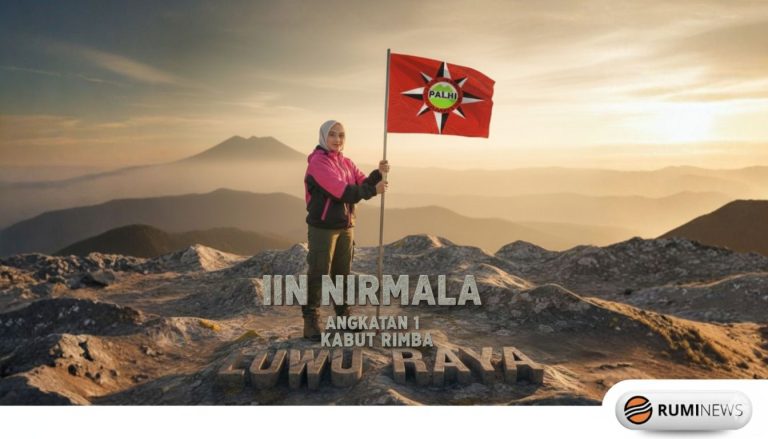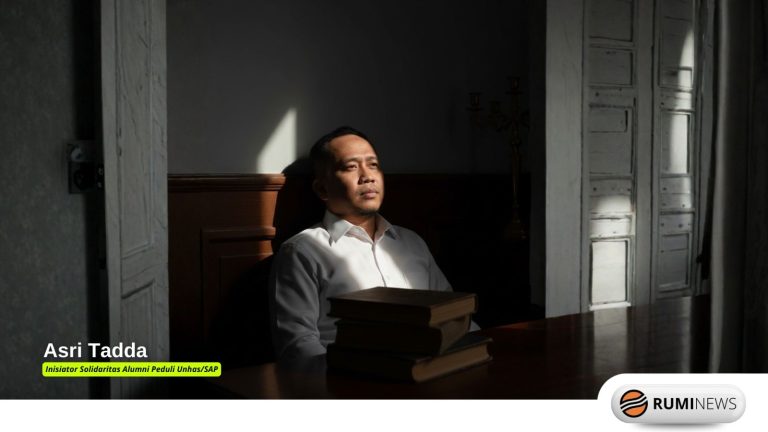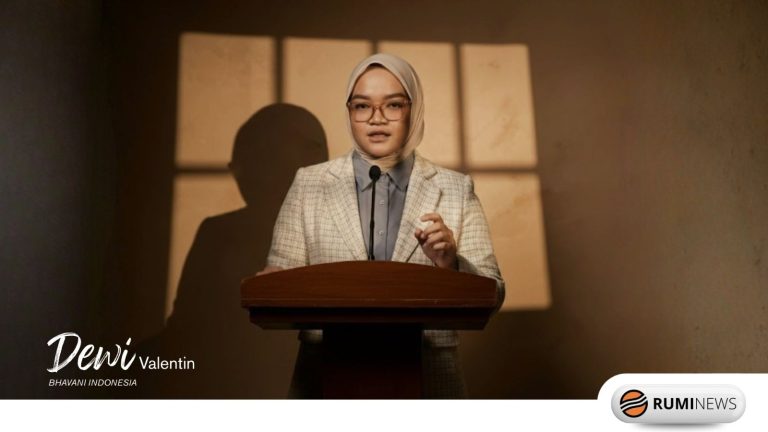ruminews.id – Amerika Serikat selalu piawai memainkan peran ganda (baca: Munafik) di panggung dunia. Satu tangan membawa pidato tentang demokrasi dan HAM, tangan lain sibuk mengunci brankas sumber daya negara lain. Venezuela adalah cermin paling jujur dari kelicikan itu. Cermin yang kalau AS mau bercermin, mungkin akan retak karena malu.
Di atas kertas, Venezuela disebut “gagal” karena salah urus ekonomi. Di balik layar, negara itu dicekik secara sistematis lewat sanksi ekonomi yang brutal. Ibaratnya, seseorang diceburkan ke sungai, lalu ketika ia hampir tenggelam, si pencebur berteriak, “Lihat! Dia tidak bisa berenang.” Sejak sanksi finansial dan embargo minyak diberlakukan, akses Venezuela terhadap pasar global, sistem perbankan internasional, dan teknologi energi diputus. Pendapatan negara anjlok, impor obat dan pangan tersendat, mata uang terjun bebas. Lalu Washington menunjuk semua itu sebagai bukti “kegagalan sosialisme”. Logika seperti ini hanya masuk akal di ruang rapat imperium, bukan di kelas filsafat dasar.
Ironinya semakin kental ketika kita ingat bahwa Venezuela duduk di atas cadangan minyak terbesar di dunia. Tapi anehnya, justru negara dengan cadangan minyak raksasa itu “tidak boleh” menjual minyaknya secara bebas. Mengapa? Karena minyak Venezuela tidak lagi tunduk pada kepentingan korporasi energi AS. Maka resep lama kolonialisme pun dikeluarkan dari lemari. Delegitimasi pemerintah, perang narasi, sanksi ekonomi, dan tentu saja dukungan terselubung pada oposisi yang lebih “kooperatif”. Ini bukan diplomasi, tapi lebih tepat disebut perampokan berseragam hukum internasional versi Washington.
Amerika juga gemar berbicara soal penderitaan rakyat Venezuela, seolah-olah penderitaan itu jatuh dari langit. Padahal, laporan demi laporan dari lembaga internasional menunjukkan bahwa sanksi ekonomi berkontribusi langsung pada krisis kemanusiaan disana, mulai dari kelangkaan obat, runtuhnya layanan publik, dan kemiskinan yang melonjak. Namun di telinga pejabat AS, fakta-fakta ini berubah menjadi noise yang tidak penting. Yang penting adalah menjaga narasi bahwa AS selalu di sisi “kebebasan”, meski kebebasan itu datang bersama kelaparan.
Lebih tragis lagi, AS mengklaim menentang kolonialisme, sambil mempraktikkan kolonialisme gaya baru. Tidak perlu kapal perang dan bendera ditancapkan. Cukup dengan sanksi, kontrol dolar, dan tekanan diplomatik. Ini kolonialisme finansial di mana wilayah tidak dijajah, tapi nadi ekonominya dikuasai. Kalau dulu kolonialisme merampas tanah dan rempah, kini kolonialisme merampas akses pasar dan sistem pembayaran. Bedanya hanya kosmetik, esensinya sama, yaitu keserakahan!.
Dan jangan lupa standar ganda yang sudah menjadi ciri khas. Ketika negara lain melakukan nasionalisasi sumber daya, itu disebut “otoritarian” dan “ancaman demokrasi”. Tapi ketika AS dan sekutunya melindungi korporasi energi mereka dengan intervensi politik dan militer, itu disebut “menjaga stabilitas global”. Seolah-olah demokrasi hanya sah jika hasilnya menguntungkan Wall Street.
Venezuela tentu saja bukan negara tanpa masalah. Korupsi, salah urus, dan konflik politik internal adalah fakta yang tidak perlu disangkal. Tapi menjadikan masalah internal itu sebagai dalih untuk menghancurkan ekonomi sebuah bangsa adalah bentuk kemunafikan kelas dunia. Seorang filsuf mungkin akan berkata: ini bukan soal ideologi, ini soal kerakusan yang disamarkan sebagai moralitas.
Pada akhirnya, kisah Venezuela membuka mata kita tentang satu hal sederhana bahwa penderitaan rakyat sering kali bukan akibat kegagalan bangsa itu sendiri, tapi hasil dari permainan kuasa global yang dingin dan kalkulatif. Amerika Serikat boleh terus berkhotbah tentang demokrasi, tapi selama praktiknya adalah mencekik negara lain demi kepentingan sendiri, khotbah itu tak lebih dari brosur iklan yang indah di kata-kata, busuk di kenyataan. Jika ini disebut kepemimpinan global, maka dunia sedang dipimpin oleh kemunafikan yang sangat keji, dan Venezuela telah membayarnya dengan terlalu mahal.
[Erwin]