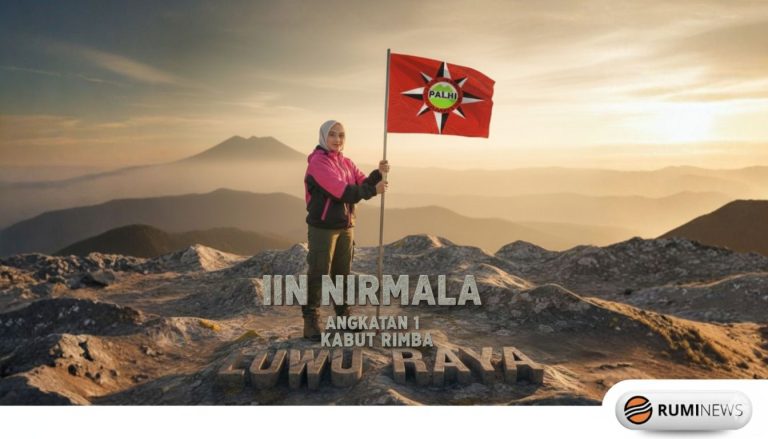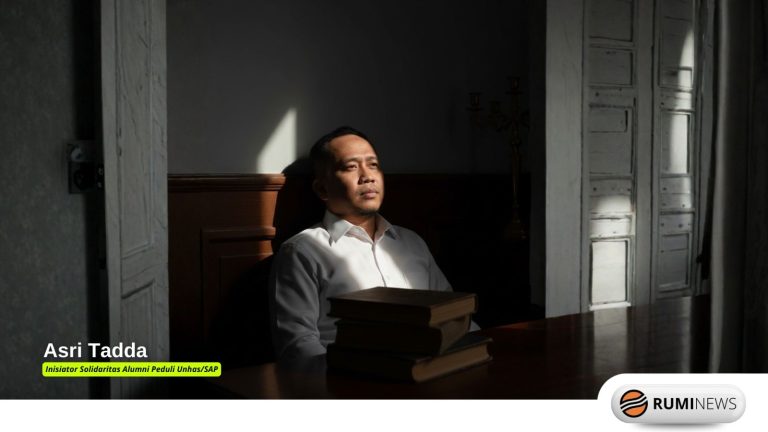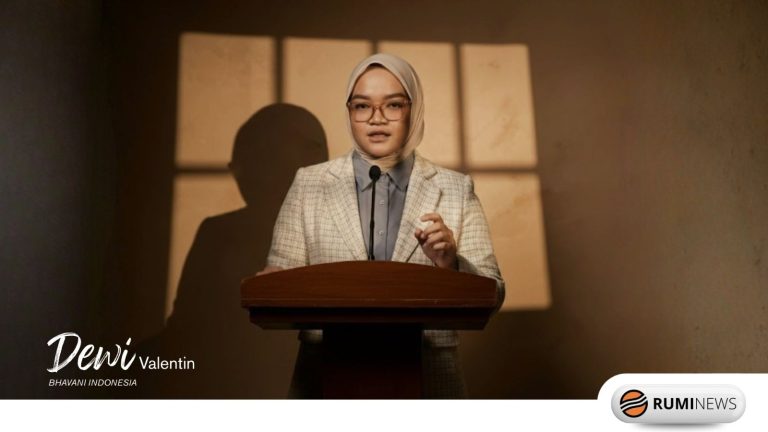ruminews.id – Mahasiswa terus diyakinkan bahwa ketidakpastian hari ini adalah harga wajar demi mobilitas esok hari. Kerja paruh waktu tanpa jaminan disebut “melatih mental”, magang tanpa upah dipromosikan sebagai “investasi pengalaman”, kompleksitas akademik dijanjikan sebagai “penjamin mutu” calon sarjanawan, dan beban biaya hidup dianggap fase sementara sebelum stabilitas datang. Masalahnya, narasi itu bertahan bukan karena benar, tetapi karena terus diulang. Di tengah dunia kerja yang makin rapuh, janji mobilitas tersebut lebih menyerupai ilusi yang diwariskan turun-temurun; sementara mahasiswa, sejak masih di bangku kuliah, sudah dilatih hidup sebagai prekariat tanpa pernah diajak membicarakan apa yang terjadi jika krisis benar-benar datang.
Diskursus terkait komunitas prekariat terbilang jarang terdengar sebagai bahan pembicaraan masyarakat secara umum. Kajian terkait “prekariat” paling tidak hanya ditemui pada referensi akademik disiplin ilmu sosio-antropologi dan semacamnya. Namun, hal tersebut bukan berarti masyarakat awam –kami menyebutnya grassroot society– tidak memahami fenomena munculnya komunitas prekariat itu sendiri. Pada dasarnya, maraknya kebijakan bernuansa populis beberapa dekade terakhir di Indonesia, secara fluaktuatif meningkatkan kesadaran kolektif masyarakat tentang pentingnya melek politik, dan secara tidak langsung turut membentuk kelas sosial baru di kemudian hari yang justru menjadi mayoritas, yakni komunitas prekariat.
Secara harfiah, prekariat berasal dari perpaduan kata “precarious” yang berarti rentan; dan “proletariat” yang identik dengan kelas pekerja. Guy Standing (2011) dalam bukunya “The Precariat: The New Dangerous Class”mempopulerkan istilah “prekariat” sebagai kelas sosial baru yang terhubung dengan dampak dari globalisasi serta instabilitas politik. Guy Standing juga memproyeksikan komunitas prekariat sebagai golongan yang mengalami ketidakpastian pendapatan, ketidakpastian kerja, ketiadaan perlindungan sosial, posisi tawar rendah, dan ketidakjelasan identitas. Di Indonesia, kategorisasi pekerjaan prekariat cenderung bias, namun merujuk beberapa sumber setidaknya ojek online, freelancer, konten kreator, beberapa industri hiburan dan semacamnya merupakan contoh konkret kehadiran prekariat di tengah masyarakat, dan notabenenya itu diminati dan justru menjadi sumber penghasilan alternatif bagi sebagian orang.
Indonesia merupakan salah satu negara dengan populasi prekariat terbesar di dunia berdasarkan persentasenya. Badan Pusat Statistik (BPS) pada Februari 2025 mencatat bahwa jumlah pekerja di sektor informal di Indonesia mencapai 86,58 juta orang. Artinya, sekitar 59,40% dari total angkatan kerja skala nasional bekerja secara informal. Data ini menunjukkan bahwa mayoritas tenaga kerja hidup dalam sistem penjaminan kerja yang rapuh dan berpotensi rentan terhadap krisis ekonomi. Di lapangan, apabila data tersebut betul mengaktual maka itu menjadi sebuah anomali mengingat bahwa Indonesia dicanangkan mengalami pertumbuhan ekonomi 5,04% per triwulan ketiga tahun 2025 (BPS, 2025). Artinya, angka pertumbuhan tersebut bergantung pada mayoritas pekerja yang mengalami ketidakpastian dunia kerja.
Lantas, Apa Kaitannya dengan Mahasiswa?
Di Indonesia, ada satu kepercayaan kolektif masyarakat bahwa perguruan tinggi seperti universitas tak lebihnya hanya sebagai mesin pencetak tenaga kerja. Ada kabar baik dan kabar buruk apabila kepercayaan kolektif tersebut ternyata betul terjadi dan masif. Kabar baiknya adalah daya serap tenaga kerja sejalan dengan jumlah lulusan sarjana dari seluruh perguruan tinggi. Sementara kabar buruknya adalah hal tersebut terjadi di Indonesia. Menurut laporan pemerintah dan BPS, per Februari 2025 terdapat sekitar 1,01 juta lulusan universitas (termasuk S1) yang menganggur di Indonesia, bagian dari total sekitar 7,28 juta pengangguran. Secara tersirat, data tersebut dapat diinterpretasikan mendukung sekaligus membantah kepercayaan kolektif yang disampaikan di awal.
Pada dasarnya, lapangan kerja di Indonesia secara keseluruhan tidak dapat langsung menampung semua orang, baik dari segi kuantitas ataupun kualitas. Oleh sebab itu, peningkatan kualifikasi menjadi salah satu opsi untuk dapat bertahan di industri yang serba selektif dan kompetitif. Stereotipe sebagian besar masyarakat Indonesia, terutama kelas sosio-ekonomi menengah ke bawah menganggap pendidikan tinggi menjadi ruang bagi mereka meningkatkan peluang sejahtera alias kualifikasi sembari mengisi waktu “menganggur” pasca lulus sekolah menengah dengan hal yang edukatif –dalam hal ini berkuliah. Stereotipe tersebut tak dapat dipungkiri menjadi bagian dari kesadaran kolektif masyarakat dan menjadi landasan mengapa mahasiswa menjadi komunitas prekariatik –setidaknya secara temporer.
Kompleksitas identitas prekariat semakin nampak dalam hal sulitnya industri menyerap freshgraduate yang turut menjadi alasan betapa rapuh dan tidak stabilnya kondisi sosioekonomi mahasiswa. Hal tersebut turut menjadi latar belakang mengapa kebijakan-kebijakan pendidikan di negeri ini terkesan transaksional dan mengekor pada logika industri. Tak heran apabila kurikulum pendidikan tinggi seakan menyiapkan para mahasiswa menjadi orang yang sesuai dengan kriteria perusahaan, program seperti magang mandiri, studi independen, pembatasan masa studi 5 tahun dan lain sebagainya betapapun memiliki alasan kuat, namun perlu dikoreksi. Selain karena alasan transaksional, banyak dampak negatif berkelanjutannya, salah satunya disorientasi perguruan tinggi yang tadinya sebagai laboratorium ide dan gagasan untuk mencetak problem solver, menjadi pabrik tenaga kerja yang tunduk buta terhadap sistem dan logika industri yang tidak stabil.
Krisis yang Jarang Dibicarakan
Wabah Covid-19 pada tahhun 2020 silam menjadi momen telanjang yang membongkar posisi nyata mahasiswa sebagai prekariat laten. Ketika aktivitas ekonomi berhenti, kelompok pertama yang terdampak adalah mereka yang berada di luar skema perlindungan formal: pekerja informal, buruh kontrak, dan mahasiswa pekerja paruh waktu. Banyak mahasiswa kehilangan sumber nafkah seketika—pekerjaan kafe, toko, proyek lepas —tanpa pesangon, tanpa jaring pengaman, dan tanpa status sebagai “korban PHK” yang berhak atas bantuan negara. Di saat bersamaan, biaya pendidikan tidak otomatis berhenti. Fakta ini menunjukkan bahwa mahasiswa tidak pernah benar-benar diposisikan sebagai subjek sosial rentan, melainkan sebagai individu yang diasumsikan selalu mampu menanggung risiko sendiri, meski secara material mereka berada dalam kondisi yang sangat rapuh.
Pandemi juga memperlihatkan kegagalan struktural kampus dalam melindungi mahasiswanya. Perkuliahan daring dipaksakan seolah-olah semua mahasiswa memiliki perangkat, jaringan internet, dan ruang belajar yang layak. Bantuan kuota dan subsidi hadir secara terbatas dan tidak menyentuh akar persoalan. Kampus lebih sibuk memastikan kalender akademik tetap berjalan dibanding memastikan mahasiswa dapat bertahan hidup secara layak. Dalam situasi ini, universitas tampak tidak memiliki protokol krisis sosial; yang ada hanya protokol administratif dan akademik. Ini menegaskan bahwa kampus telah bergeser dari institusi sosial menjadi institusi manajerial yang mengelola mahasiswa sebagai angka, bukan sebagai manusia.
Kondisi tersebut memperlihatkan bagaimana proses prekarisasi mahasiswa bekerja secara struktural. Mahasiswa tidak hanya dipersiapkan menghadapi dunia kerja yang tidak pasti, tetapi sejak awal sudah dilatih hidup di dalam ketidakpastian itu sendiri. Mereka didorong bekerja sambil kuliah tanpa perlindungan, menanggung beban biaya hidup sendiri, dan menerima ketidakstabilan sebagai bagian dari“proses pendewasaan”. Pola ini identik dengan ciri-ciri utama kelas prekariat: pendapatan tidak tetap, ketiadaan jaminan sosial, dan posisi tawar yang lemah. Dengan kata lain, mahasiswa bukan sekadar calon prekariat, tetapi sudah menjadi bagian dari prekariat dalam bentuk yang disamarkan.
Dampak struktural yang lebih serius adalah rusaknya fungsi pendidikan tinggi sebagai alat mobilitas sosial. Alih-alih menjadi jalan keluar dari kemiskinan dan ketidakpastian, kuliah justru memperpanjang fase kerentanan ekonomi. Mahasiswa dipaksa bertahan lebih lama dalam kondisi tanpa kepastian dengan janji bahwa stabilitas akan datang setelah lulus. Namun pandemi membuktikan bahwa janji tersebut tidak memiliki dasar yang kuat. Ketika krisis datang, gelar akademik tidak serta-merta melindungi, dan transisi dari kampus ke dunia kerja justru menjadi semakin buntu. Di titik ini, pendidikan tinggi tidak lagi memutus rantai ketimpangan, melainkan mereproduksinya dalam bentuk baru.
Oleh karena itu, hubungan antara mahasiswa dan prekariat tidak bisa dipahami sebagai kondisi sementara atau kebetulan akibat krisis. Ia adalah hasil dari desain sosial dan kebijakan yang secara sistematis memindahkan risiko dari negara dan institusi ke individu mahasiswa. Selama mahasiswa terus diperlakukan sebagai subjek yang “sedang belajar”, bukan sebagai kelompok sosial rentan, maka setiap krisis baru akan selalu menempatkan mereka di posisi paling lemah. Jika kondisi ini dibiarkan, maka yang sedang dibangun bukan generasi terdidik yang berdaya, melainkan generasi prekariat baru yang lahir dari bangku kuliah itu sendiri.
Referensi & Bacaan Lanjutan: