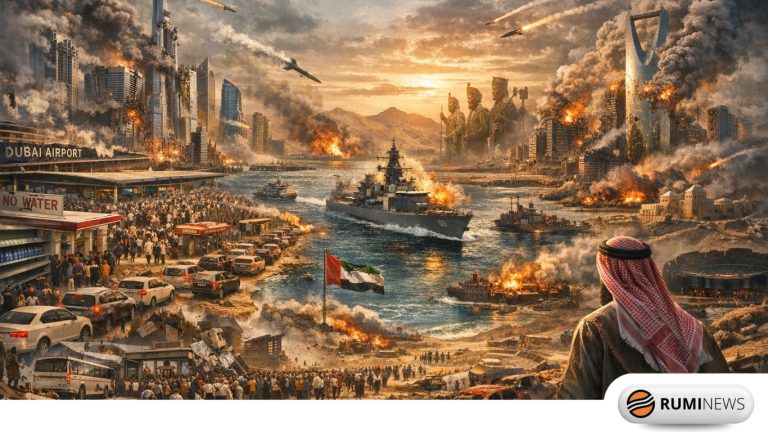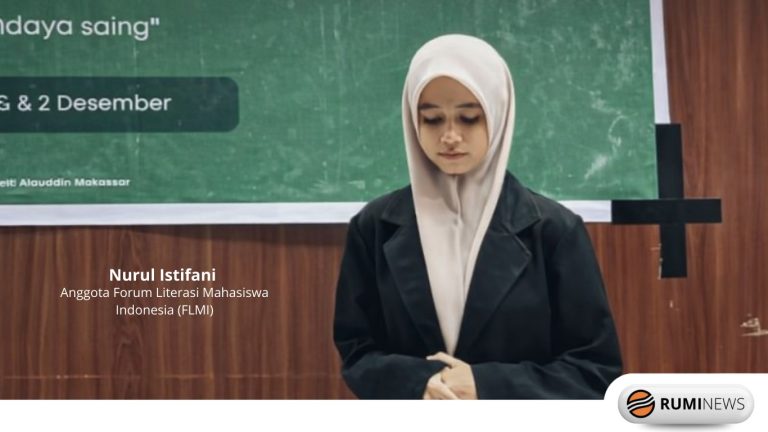ruminews.id – “Orang tidak dapat memiliki demokrasi tanpa kebebasan beragama”. Begitu tutur Jose Casanova.
Konstitusi negara ini (UUD 1945), telah menetapkan Indonesia bukan sebagai sebuah negara agama, melainkan sebagai sebuah negara hukum demokratis modern yang menjamin kebebasan beragama para warganya. Meskipun demikian, banyak pemberitaan yang kita dengar baik di televisi, surat kabar, media sosial danmungkin kita saksikan langsung tindakan-tindakan pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan (KBB).
Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh lembaga SETARA Institute,pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan (KBB) di Indonesia menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Pada 2022 tercatat 175 peristiwa dengan 333 tindakan pelanggaran KBB, sedangkan pada 2023 jumlahnya meningkat menjadi 217 peristiwa dengan 329 tindakan. Hingga 25 Mei 2024, jumlah tersebut kembali naik dengan total 260 peristiwa dan 402 tindakan pelanggaran.Bentuk-bentuk pelanggaran tersebut beragam di antaranya, penolakan pembagunan rumah ibadah, perusakan tempat ibadah, pembubaranpaksa kegitan ibadah, persekusi atas minoritas, seperti terjadi padakepercayaan lokal, Ahmadiyah, Syiah, ikut mengisi lanskap politis Indonesia.
Tulisan ini mengidentifikasi dua faktor dominan yang menyebabkan beragam bentuk tindakan pelanggaran beragama/berkeyakinan (KBB), serta menghadirkan gagasan yang memungkikan Indonesia dapat keluar dari problem tersebut.
Dua Faktor Dominan
Penulis mengidentifikasi terdapat dua faktor yang menyebabkan tindakan pelanggaran KBB. Pertama, negara tidak adil bagi Kelompok kepercayaan minoritas. Meskipun para pendiri bangsa merancang Indonesia modern yang merdeka tidak didasarkan pada agama tertentu, melainkan dibangun atas prinsip persatuan seluruh warga negara dengan hak dan kewajiban yang sama, tanpa memandang latar belakang keagamaan. Seperti ucapan Soekarno dalam salah satu pidatonya “Kita hendak mendirikan suatu negara semua buat semua. Bukan buat satu orang, bukan buat satu golongan tetapi semua buat semua. Memang, rakyat Bali menyambut proklamasi dengan gegap gempita. Agamanya adalah Hindu-Bali. Tetapi mereka menyambut proklamasi ini ialah karena proklamasi ini didasarkan kepada Pancasila. Inilah dasar yang menjamin keutuhan bangsa kita yang beraneka agama, yang beraneka adat istiadat, yang beraneka suku”.
Dengan prinsip kesetaraan seluruh warga negara tanpa memandang latar belakang indentitas primodial yang diletakkan oleh para pendiri bangsa tersebut, negara seharusnya bersikap netral terhadap seluruh kelompok kepercayaan yang hidup dalam masyarakat. Bersikap netral yang saya maksud adalah sikap proaktif menjamin kebebasan agama untuk semua golongan dan tidak mengistimewakan kelompok agama tertentu. Namun dalam praktiknya, banyak ditemukan berbagai kebijakan negara yang membuka ruang diskriminasi terhadap kelompok minoritas.
Salah satu contohnya adalah Peraturan Bersama Menteri (PBM) 2006tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah. Dalam salah satu pasal peraturan tersebut memuat tentang syarat dan prosedur pendirian rumah ibadah seperti daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadah paling sedikit 90 orang yang disahkan oleh pejabat setempat, dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa, rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota.
Aturan tersebut menjadi salah satu penyebab munculnya kekerasan berbasis agama. Ketika kelompok minoritas berusaha mendapatkan dukungan 60 warga sekitar, proses ini sering menimbulkan penolakan, penggalangan massa, hingga pelarangan aktivitas ibadah yang disertai ancaman dan kekerasan fisik. Di banyak kasus, kelompok yang menolak kemudian menggunakan pasal ini sebagai legitimasi untuk membubarkan kegiatan ibadah, menyerang bangunan yang sedang dibangun, atau menekan aparat agar menutup rumah ibadah.
Selain PBM 2006, masih ada beberapa regulasi yang membuka ruang terjadinya tindakan KBB, seperti UU PNPS No. 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agma, Pasal Penodaan Agama dalam KUHP (Pasal 156a), keterbatasan pengakuan agama dalam administrasi kependudukan, serta berbagai peraturan daerah bernuansa agama yang membatasi kebebasan kelompok minoritas. Tidak hanya regulasi, sejumlah laporan SETARA Institute, menunjukkan aktor negara seperti pemerintah daerah, TNI-POLRI, maupun kejaksaan, membiarkan dan bahkan terlibat dalam tindakan intolerasi atau pelanggaran KBB.
Faktor Kedua adalah pandangan fundamentalisme agama dan sektarianisme di sebagian kalangan pemeluk agama di Indonesia.Fundamentalisme agama sendiri adalah sebuah pemahaman yang mengklaim kebenaran tunggal, dan bahkan juga memaksakan preferensi atas kebenaran tunggal itu sebagai kebenaran yang mesti dianut oleh yang lain. Implikasi dari pemahaman fundamentalismeagama tersebut yang memotivasi lahirnya tindakan-tindakanpelanggaran KBB.
Para pelaku tindakan tidak terpuji tersebut banyak datang dari kelompok yang mengidentifikasi dirinya sebagai bagian dari umat Islam, agama dengan jumlah pemeluk terbesar di Indonesia. Dan sebagaiamana jamak diketahui pelaku tindakan KBB mendapatjustifikasi pada sejumlah ayat Al-Qur’an yang, dalam istilah Mun’im Siryy, bersifat polemik. Bersifat polemik menurut beliau adalah ayat-ayat yang bukan saja memandang dan menggambarkan agama-agama lain secara negatif, melainkan juga mengkritiknya, baik dari sisi doktrin maupun aspek perilaku sosial. Jadi tindakan pelangaran KBB dengan justifikasi relegius bisa dipahami sebagai atas nama Tuhan dengan motivasi tindakan mereka sebagai ibadah.
Mun’im Siryy mendorong agar para intelektual Islam melakukan penelitian ilmiah untuk menelaah unsur-unsur polemis dalam Al-Qur’an. Upaya ini penting karena ayat-ayat polemik kerapdisalahgunakan oleh kelompok radikal untuk mencari pembenaran keagamaan atas tindak kekerasan mereka terhadap kelompok lain.Melalui penelitian yang kritis dan historis, unsur-unsur polemis tersebut dapat dipahami secara lebih tepat, dalam rangka memahami keyakinan kita secara lebih baik, menjawab tuntutan dunia modern, dan dapat memberi sumbangsih bagi kemajuan masyarakat.
Masih menurut Mun’im Siryy, pemahaman terhadap teks-teks Al-Qur’an yang bersifat polemik tidak bisa dilepaskan dari konteks historisnya. Narasi polemik dalam Al-Qur’an tersebut sebenarnya merupakan cerminan interaksi Nabi Muhammad dengan komunitas agama lain pada masanya, seperti Yahudi, Kristen, dan kaum penyembah berhala di Mekah. Dalam konteks, itu polemik dalam Al-Qur’an berpusat pada dua hal utama: pengakuan terhadap kenabian Muhammad dan keaslian wahyu Al-Qur’an. Pada tahap awal kemunculan Islam, komunitas Muslim menghadapi kondisi yang kurang bersahabat. Maka, tidak mengherankan jika Al-Qur’an menggunakan bahasa yang tegas untuk menanggapi pihak-pihak yang mencoba menghambat atau menghancurkan dakwah Islam. Bahasa polemik ini bukanlah untuk memicu kebencian, melainkan untuk menegaskan identitas umat Muslim. Ini adalah cara Al-Qur’an untuk membedakan komunitas Muslim dari komunitas lain dan memperkuat keyakinan mereka di tengah tantangan yang ada. Sama seperti kitab suci lainnya, Al-Qur’an secara jujur melukiskan semangat dan sikap masyarakat Muslim awal dalam panggung sejarah.
Dengan memahami konteks tersebut, Mun’im Sirry menegaskanbahwa teks-teks polemis dalam Al-Qur’an dapat ditafsirkan ulang sesuai kebutuhan zaman. Di dunia modern yang menjunjung tinggi sikap toleransi dan penghormatan terhadap keyakinan agama orang lain, ayat-ayat tersebut perlu dipahami dalam semangat yang sejalan dengan nilai-nilai perdamaian. Penafsiran semacam ini, menurut Mun’im, bukanlah bentuk mengubah agama, tetapi bagian dari tradisi panjang tafsir dalam Islam yang selalu menyesuaikan pemaknaan teks dengan perkembangan sosial, etis, dan intelektual manusia.
Titik Balik Menuju Masyarakat yang Toleran
Untuk keluar dari lingkaran tindakan pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan yang terus terjadi menurut saya, Indonesiamembutuhkan penataan ulang pada dua ranah: ranah kenegaraan, yakni hubungan vertikal antara masyarakat warga dan negara, serta ranah kemasyarakatan atau masyarakat warga (civil society), yakni hubungan horizontal di antara kelompok-kelompok agama.
Pada ranah kenegaraan, negara harus kembali pada prinsipkeadialan yang menjadi fondasi berdirinya. Tanpa keadilan seperti kata Cicero mustahil ada republik. Dalam masyarakat yang majemukseperti Indonesia, negara harus netral dari apa yang disebut comprehensive religious doctrines atau ajaran agama tertentu. Negara yang adil bagi semua adalah negara yang dibangun di atas konsepsi tentang yang adil, bukan di atas konsepsi tentang yang baik menurut keyakinan relegius tertentu. Karena konsep tentang yang baik sangat beragam dan sering kali bertentangan, negara tidak boleh memaksakan doktrin atau nilai keagamaan tertentu melalui kebijakan publik.
Campur tangan negara dalam perkara-perkara privat warganya, misalnya dengan mengeluarkan kebijakan yang mengatur cara beribadat, membatasi keyakinan, melarang pernikahan bedah agama, ataupun mengeluarkan tuduhan penyesatan di dalam masyarakat majemuk akan melanggar toleransi dan bertentangan dengan negara hukum demokratis.
Sejalan dengan itu, aturan-aturan yang membuka ruang intoleransi, seperti PBM 2006, pasal-pasal penodaan agama yang multitafsir, serta regulasi daerah yang bias kelompok mayoritas, perlu ditinjau ulang.
Negara musti juga memperkuat penegakan hukum terhadap pelaku intolerasnsi. Melakukan investigasi yang komprehensif, independen, imparsial dan efektif untuk memeriksa kasus intimidasi dan serangan terhadap minoritas agama mana pun dan mengadili mereka yang bertanggung jawab sesuai dengan standar internasional tentang peradilan yang adil dan memberikan pemulihan bagi korban.
Pada ranah kemasyarakatan atau hubungan horizontal di antara kelompok-kelompok agama. Dalam bagian ini saya mengunakan gagasan Nurcholish Madjid tentang titik-temu agama-agama. Nurcholish Madjid atau yang lebih dikenal Cak Nur dalam buku Islam Agama Kemanusiaan, mengatakan diskusi tentang asas kerukunan umat beragama secara langsung maupun tidak langsung mengasumsikan adanya kemungkinan penganut agama bertemu dalam landasan yang sama (common platform).
Titik–temu agama-agama ini meskipun terbatas hanya kepada hal-hal yang prinsipil, seperti nilai kemanusiaan, keadilan, dan komitmen untuk hidup damai. Adapun hal-hal yang rinci seperti ekspresi-ekspresi simbolik dan formalistik, tentu sulit dipertemukan. Masing-masing agama, memiliki idiomnya yang khas dan bersipat esoterik, yakni, hanya berlaku secara intern. Oleh sebab itu, ikut-campur seorang penganut agama dalam urusan rasa kesucian agung dari agama lain adalah tidak rasional dan absurd.
Cak Nur juga menekankan hubungan harmonis di antara pemeluk agama hanya dapat terwujud apabila kita menyadari kemajemukan atau pluralitas sebagai kenyataan yang telah menjadi kehendak tuhan.Pluralitas bukan sekadar fakta sosial, melainkan sunatullah atau ketetapan Ilahi yang menandai bahwa manusia memang diciptakan berbeda dalam suku, bangsa, dan keyakinan. Kesadaran akan pluralitas sebagai bagian dari desain Tuhan ini menjadi fondasi moral bagi para pemeluk agama di Indonesia untuk saling menghargai, penuh pengertian, bersedia belajar kebenaran dari yang lain, dan berkerja sama dalam membangun kehidupan yang damai dan berkeadaban.
Sumber:
Budi Hardirman F (2017), Demokrasi dan Sentimentalitas: Dari Bangsa Setan-setan, Radikalisme Agama, Sampai Post-Sekularisme (PT Kanisius)
Laporan Setara Institute
Madjid, Nurcholish (1995), Islam Agama Kemanusiaan: Membagun Visi Baru Islam Indonesia (Dian Rakyat Jakarta).
Sirry Mun’im (2013), Polemik Kitab Suci: Tafsir Reformis atas Kritik AlQur’an terhadap Agama Lain (Gramedia Pustaka Utama)