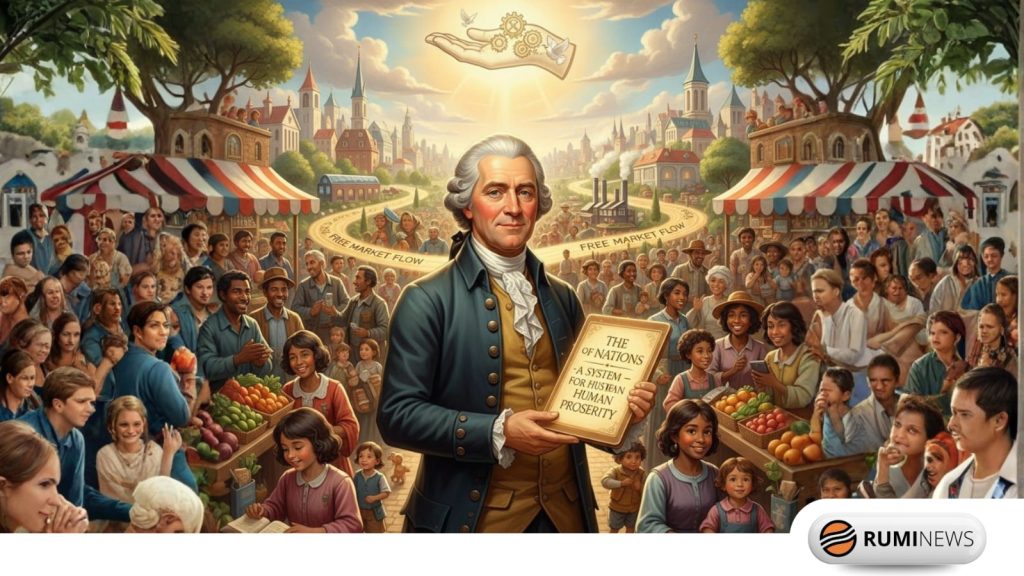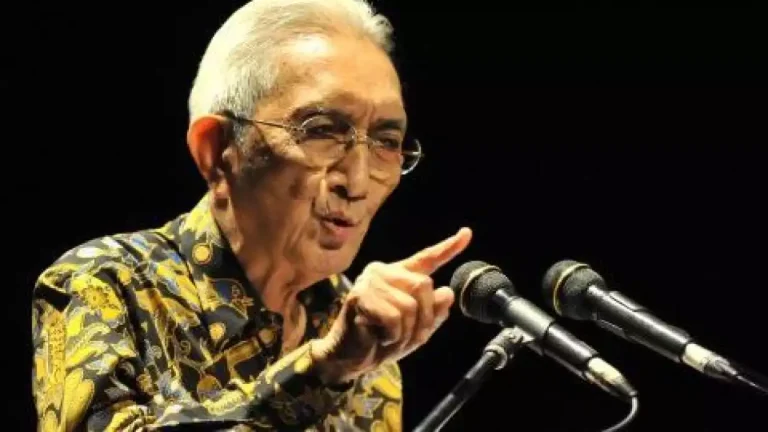ruminews.id – Kata “kapitalisme” sering membuat sebagian orang spontan cemberut, seolah-olah Kapitalisme adalah iblis ekonomi yang mencuri kesejahteraan rakyat dan menimbun harta di tangan segelintir orang. Tapi mari kita tarik napas sebentar, lepaskan semua prasangka, dan coba melihatnya bukan dari kacamata ideologi, melainkan dari sisi moralitas manusia yang bekerja dan berinovasi.
Adam Smith, yang kerap dicap sebagai “bapak kapitalisme”, sering kali disalahpahami. Banyak yang mengutip The Wealth of Nations (1776) dan berhenti di sana, seolah kapitalisme hanyalah soal “tangan tak terlihat” yang mengatur pasar. Padahal, Smith yg seorang filsuf dan profesor filsafat moral, lebih dulu menulis The Theory of Moral Sentiments (1759), sebuah karya etis yang menjadi fondasi moral dari seluruh pemikirannya. Dalam buku itu, Smith menulis dengan lembut namun tegas:
“No society can surely be flourishing and happy, of which the far greater part of the members are poor and miserable.”
(Tiada masyarakat yang dapat benar-benar makmur dan bahagia bila sebagian besar warganya hidup miskin dan sengsara.)
Kapitalisme pada dasarnya lahir dari dorongan paling manusiawi yaitu keinginan untuk memperbaiki hidup melalui kerja, kreativitas, dan tanggung jawab pribadi. Dalam bentuk aslinya, kapitalisme tidak mengajarkan kerakusan, melainkan menekankan meritokrasi (bahwa siapa yang bekerja keras, berpikir cerdas, dan berani mengambil risiko pantas mendapatkan hasil yang sepadan). Bukankah itu sejalan dengan nilai universal keadilan? Bahkan, dalam Islam pun, semangat itu diakui. Rasulullah sendiri seorang pedagang, bukan birokrat. Ia tidak membenci laba, hanya mengutuk riba dan tipu daya.
Masalahnya bukan pada kapitalisme itu sendiri, tapi pada manusia yang lupa bahwa kekayaan bukan tujuan, melainkan amanah. Kapitalisme yang sehat justru mengandung semangat keadilan distributif dimana keuntungan yang dihasilkan tidak berhenti di saku individu, tetapi turut mengalir dalam ekosistem sosial lewat pajak yang adil, kesempatan kerja, atau inovasi yang mempermudah hidup orang banyak. Kapitalisme yang bermoral bukanlah soal siapa yang paling kaya, tapi siapa yang paling mampu membuat nilai tambah bagi sesama.
Sayangnya, dalam praktik modern, kapitalisme sering berubah menjadi kompetisi rakus tanpa moral. Tapi bukankah itu kesalahan kita sendiri, bukan sistemnya? Kapitalisme tidak pernah menyuruh kita memonopoli, menindas, atau menyuap. Kapitalisme hanya menyediakan ruang bagi manusia untuk berkreasi dan diuji kejujurannya. Sama seperti pisau dapur, bisa digunakan untuk memasak atau melukai. Semua tergantung siapa yang memegangnya.
Yang menarik, jika kita membaca lebih dalam, semangat kapitalisme awal sesungguhnya sangat dekat dengan etika kerja Protestan dan juga prinsip keadilan ekonomi dalam Islam. Keduanya sama-sama memuliakan kerja keras, menghargai kejujuran, dan mengutuk kemalasan. Islam bahkan menegaskan bahwa “tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah.” Itu bukan slogan kapitalis tapi prinsip moral universal tentang martabat manusia yang produktif.
Di sinilah seharusnya kita menempatkan kapitalisme. Bukan sebagai musuh, tapi sebagai alat. Kapitalisme akan memuliakan manusia jika dikendalikan oleh moral, dan akan menindas manusia jika dilepaskan tanpa kendali nilai. Kapitalisme yang bermoral memberi ruang bagi meritokrasi (menghargai hasil dari kerja dan bakat) sambil tetap menjaga keseimbangan sosial melalui keadilan distributif.
Jadi, mungkin bukan kapitalismenya yang harus dihapus, melainkan kerakusan yang harus disembuhkan. Sebab kapitalisme sejati bukan tentang menimbun, tapi tentang menumbuhkan. Dan di tangan manusia yang beriman pada nilai keadilan, Kapitalisme bisa menjadi motor kebaikan, bukan sumber kesenjangan.
[Erwin]