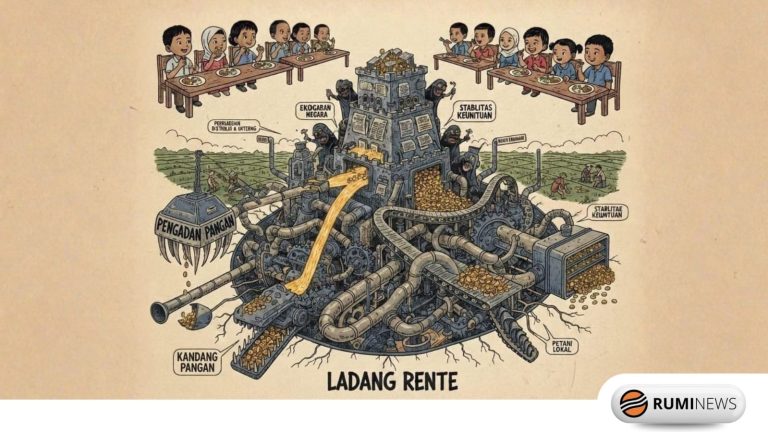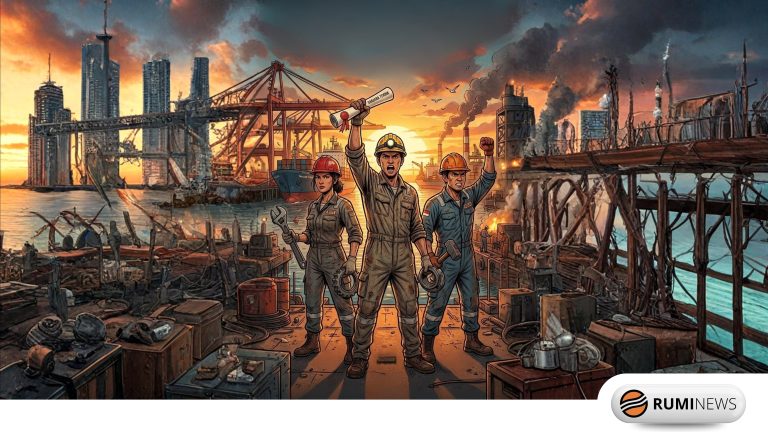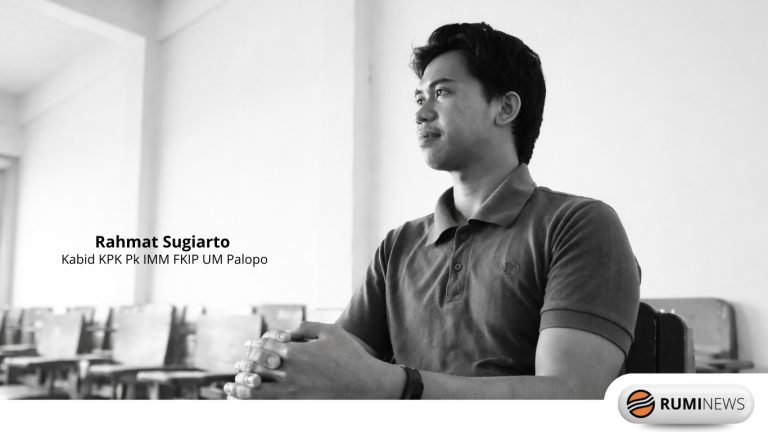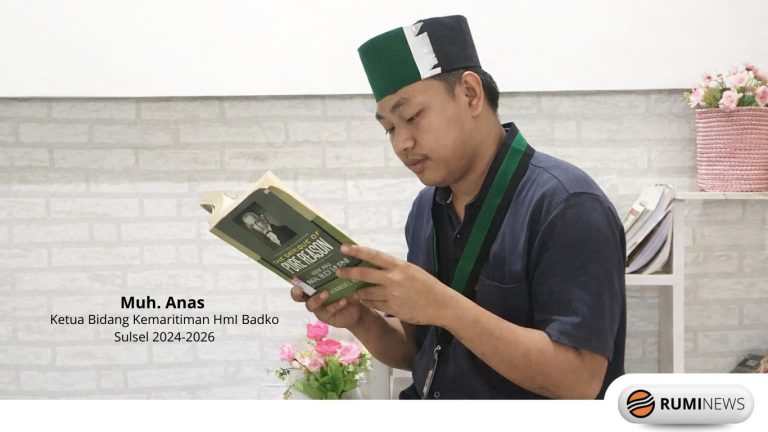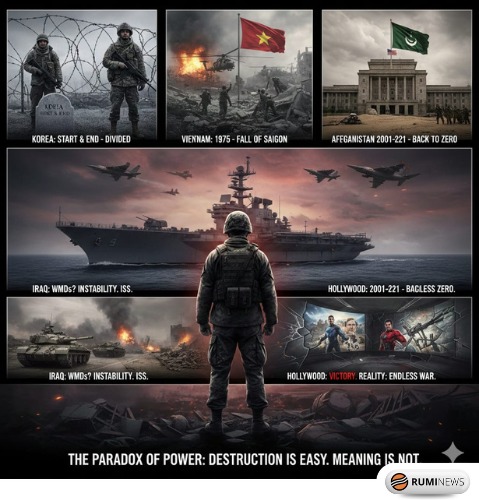ruminews.id – Beberapa pekan terakhir, linimasa saya dipenuhi oleh kabar keracunan massal dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program yang awalnya disambut hangat karena dianggap mampu memperbaiki gizi anak sekolah, kini justru ramai diperbincangkan bukan karena keberhasilan, melainkan karena kegagalannya yang paling mendasar: makanan yang seharusnya menjadi sumber kesehatan justru berbalik membawa penyakit.
Bagi sebagian orang, persoalan ini mungkin terlihat sepele dan dianggap sekadar urusan teknis atau kelalaian yang bisa segera dibenahi. Namun bagi saya, justru di situlah letak masalah seriusnya: Bagaimana mungkin sebuah program yang bertujuan memberikan gizi justru menimbulkan masalah baru di meja makan sekolah?
Yang paling mengganggu saya dari kasus ini bukan hanya soal keracunan itu sendiri, melainkan bagaimana negara meresponsnya. Respons yang cenderung mereduksi tragedi ini hanya sebagai kesalahan teknis-administratif membuat pertanyaan besar muncul: apakah negara sungguh memahami arti hak asasi manusia dalam konteks pangan yang aman? Saya khawatir, jika cara pandang semacam ini dibiarkan, masyarakat akan semakin kehilangan rasa percaya pada negara.
MBG dan Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dicanangkan dengan semangat yang tampak sederhana namun punya makna besar. Yakni, memastikan setiap anak sekolah mendapat makanan layak tanpa harus memandang status ekonomi keluarganya. Ide ini sendiri bukan lahir dari ruang kosong. Dalam visi politik, MBG diproyeksikan sebagai salah satu strategi mengatasi masalah gizi kronis di Indonesia, mulai dari stunting hingga lemahnya daya saing generasi muda. Dengan kata lain, ia bukan sekadar “program bagi-bagi makanan”, tetapi sebuah intervensi negara untuk menutup celah ketidakadilan sosial yang paling nyata: perbedaan akses pangan antara si kaya dan si miskin.
Di titik ini, program MBG bersentuhan langsung dengan prinsip hak asasi manusia. Pasal 25 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) secara tegas menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas standar hidup yang layak bagi kesehatan dan kesejahteraan dirinya serta keluarganya, termasuk pangan yang memadai. Hal ini ditegaskan kembali dalam International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 11 Tahun 2005. Artinya, negara punya kewajiban hukum untuk menjamin bahwa makanan yang dikonsumsi rakyatnya tidak hanya tersedia, tetapi juga aman dan bergizi.
Persoalannya, hak atas pangan di Indonesia sering kali berhenti di ranah konsep. Data Badan Pangan Nasional mencatat bahwa pada tahun 2023, masih ada sekitar 7,7% rumah tangga Indonesia yang mengalami kerawanan pangan sedang hingga berat (Badan Pangan Nasional, 2023). Angka ini menunjukkan betapa pentingnya program seperti MBG. Ia menjadi jawaban politik atas situasi nyata di lapangan, di mana jutaan anak masih berangkat sekolah dengan perut kosong atau hanya ditopang makanan seadanya.
Namun di balik niat baik itu, ada satu hal mendasar yang sering dilupakan, yaitu memastikan kualitas dan keamanan makanan. Di sinilah hubungan antara MBG dan HAM menemukan titik krusialnya. Hak atas pangan tidak bisa dipisahkan dari hak atas kesehatan. Pangan yang diklaim “bergizi” tapi berpotensi menimbulkan keracunan justru melanggar prinsip HAM itu sendiri. Pertanyaannya, apakah negara benar-benar serius menjadikan MBG sebagai instrumen pemenuhan hak warga, ataukah sekadar simbol politik untuk meraup simpati?
Saya melihat, problem terbesar bukan pada ide MBG itu sendiri, melainkan pada bagaimana negara menerjemahkan ide itu dalam praktik Hak atas pangan yang tidak berhenti pada kegiatan membagikan makanan, tetapi menuntut jaminan mutu, keamanan, dan keberlanjutan dalam pelaksanaannya. Tanpa pengawasan dan jaminan mutu yang memadai, MBG bisa berubah menjadi ironi, yakni program yang dirancang untuk menyehatkan anak-anak justru dapat menimbulkan ancaman baru bagi kesehatan mereka.
Masalah dalam Implementasi MBG
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memang tampak menjanjikan. Ia hadir sebagai wujud kepedulian negara terhadap anak-anak yang sering kali berangkat sekolah dengan perut kosong. Namun, kenyataan di lapangan justru jauh dari ideal. Sejak awal pelaksanaannya, program ini diwarnai berbagai kasus keracunan massal di sejumlah daerah. Menurut data resmi Kementerian Kesehatan, hingga Juli 2025 tercatat lebih dari enam ribu siswa mengalami gejala keracunan yang diduga kuat berasal dari makanan MBG. Pemeriksaan laboratorium bahkan menemukan keberadaan bakteri E. coli, Salmonella, hingga Bacillus cereus pada beberapa sampel makanan yang dikonsumsi siswa (Detik, 2025).
Saya melihat persoalan utama bukan semata pada niat baik programnya, melainkan pada kualitas pengelolaan yang belum siap menghadapi skala nasional. Laporan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyebutkan ada 13 temuan pelanggaran serius di dapur penyedia MBG yang berkaitan langsung dengan kasus luar biasa (KLB) keracunan (Kontan, 2025). Dari mulai penyimpanan bahan makanan tanpa pendingin yang layak, proses distribusi yang tidak higienis, hingga dapur yang tidak memenuhi standar sanitasi dasar.
Ahli gizi publik, Imas Arumsari dari RUKKI, menilai bahwa akar masalahnya terletak pada absennya standar keamanan pangan yang seharusnya diterapkan secara menyeluruh. Ia menegaskan bahwa setiap dapur MBG semestinya menggunakan pendekatan Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP), bukan sekadar mengandalkan pemeriksaan visual atau uji acak. Menurutnya, “Keamanan pangan bukan hanya soal memasak dengan benar, tetapi juga bagaimana sistem distribusi dan penyimpanan dijaga agar tidak menimbulkan bahaya bagi anak-anak yang mengonsumsinya” (Liputan6, 2025).
Ironinya, di beberapa wilayah justru ditemukan menu MBG yang menggunakan makanan ultra-proses seperti burger, sosis, atau spaghetti instan atau jenis makanan yang dalam banyak penelitian disebut memiliki dampak jangka panjang bagi kesehatan anak. Pakar gizi Tan Shot Yen bahkan menyebut langkah ini “keliru secara filosofi”, karena tujuan MBG mestinya membangun kebiasaan makan sehat berbasis pangan lokal, bukan memperkenalkan pola makan instan ala industri (Suaramerdeka, 2025).
Tanggapan Menteri HAM
Ketika berita keracunan massal mulai menghampiri berbagai daerah, harapan publik tertuju kepada pejabat tinggi negara untuk memberikan jawaban yang bertanggung jawab. Namun tanggapan yang muncul justru menimbulkan kegelisahan baru. Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, menyampaikan di kantor Kementerian HAM bahwa kasus keracunan massal dalam proyek MBG “tidak melanggar HAM milik korban.” Pigai menyatakan bahwa ribuan siswa yang mengalami keracunan itu “tak memenuhi unsur-unsur pelanggaran HAM”. Unsur pelanggaran HAM yang ia maksud adalah negara lalai maupun dengan sengaja membiarkan keracunan terjadi. Menurutnya, “Misalnya satu sekolah yang masaknya kurang terampil, (sehingga basi) makanannya itu kan tidak bisa dijadikan sebagai pelanggaran HAM kan.” (Tempo, 2025).
Pernyataan tersebut seolah hendak menegaskan bahwa kegagalan teknis atau administratif tidak sama dengan pelanggaran hak asasi manusia. Namun, pandangan itu menyisakan kekeliruan mendasar karena kelalaian yang terjadi secara sistematis dan berdampak luas terhadap masyarakat, seperti ribuan siswa yang jatuh sakit yang dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran HAM. Dalam kerangka teori hak asasi, negara tidak selalu harus melakukan tindakan represi agar dianggap melanggar HAM. Dari sisi hukum dan norma HAM, kegagalan negara dalam melindungi warga dari bahaya yang seharusnya dapat dicegah juga termasuk dalam pelanggaran hak asasi.
Pernyataan tersebut seolah menegaskan bahwa kegagalan teknis atau administratif tidak dapat disamakan dengan pelanggaran hak asasi manusia. Namun pandangan itu menyimpan kekeliruan mendasar karena kelalaian yang terjadi secara sistematis dan berdampak luas terhadap masyarakat, seperti ribuan siswa yang jatuh sakit, dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran HAM. Dalam kerangka teori hak asasi, negara tidak harus melakukan tindakan represif untuk dianggap melanggar HAM. Dari sisi hukum dan norma HAM, kegagalan negara dalam melindungi warga dari bahaya yang seharusnya dapat dicegah juga termasuk dalam bentuk pelanggaran hak asasi.
Pandangan ini sejalan dengan pendapat Zainal Arifin Mochtar, pakar hukum dan HAM dari Universitas Gadjah Mada, yang menegaskan bahwa negara bisa dianggap melanggar hak asasi manusia bukan hanya karena melakukan tindakan sewenang-wenang, tetapi juga karena gagal melindungi warganya dari bahaya yang dapat dicegah (Zainal Arifin Mochtar, wawancara publik, 2024). Artinya, pelanggaran HAM tidak selalu harus disertai dengan kekerasan atau niat jahat. Ketika negara tidak hadir dalam mencegah bahaya nyata yang muncul akibat kebijakan publik yang dijalankannya, maka negara telah abai terhadap tanggung jawab dasarnya sebagai pelindung hak warga negara.
Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN CESCR) dalam General Comment No. 12 juga menegaskan bahwa hak atas pangan tidak hanya mencakup ketersediaan dan keterjangkauan, tetapi juga keamanan dan kualitasnya. Dalam dokumen tersebut dinyatakan bahwa negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak atas pangan yang layak. Jika masyarakat justru menderita karena pangan yang disediakan negara tercemar atau tidak bermutu, maka negara gagal menjalankan kewajibannya untuk melindungi dan memenuhi hak atas pangan (UN CESCR, General Comment No. 12, 1999).
Di tingkat nasional, Komnas HAM secara tegas menyatakan bahwa tindakan, kebijakan, atau kelalaian negara yang menyebabkan masyarakat kehilangan akses terhadap makanan yang aman dan bergizi merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia, terutama hak untuk hidup dan memperoleh kesehatan yang layak (Siaran Pers Komnas HAM, 2023).
Karena itu, pernyataan Menteri Pigai bukan hanya bernada membela diri, melainkan juga menunjukkan cara pandang yang sempit terhadap hak asasi manusia, seolah HAM hanya relevan ketika ada tindakan kekerasan atau penindasan yang jelas.Dalam praktiknya, kesalahan administratif dan pelanggaran HAM sering kali saling berkaitan. Sistem birokrasi yang lalai hingga menyebabkan ribuan siswa keracunan tidak bisa dipisahkan dari tanggung jawab negara yang gagal menjamin keamanan pangan bagi warganya.
Yang paling mengkhawatirkan adalah dampak dari cara berpikir semacam ini. Ketika pejabat publik merasionalisasi kegagalan dengan menyebutnya sekadar masalah teknis, korban kehilangan posisi sebagai subjek hukum dan berubah menjadi angka statistik belaka. Jika negara terus menempatkan hak asasi manusia hanya dalam konteks besar dan jauh dari pengalaman hidup rakyat sehari-hari, maka keadilan akan tetap menjadi milik segelintir elit. Pada akhirnya, hak atas pangan yang aman dan hak untuk hidup sehat, dua hal yang seharusnya menjadi tanggung jawab utama negara, berisiko direduksi menjadi sekadar jargon politik tanpa makna jika tidak diikuti dengan akuntabilitas nyata.
Sebuah refleksi
Jika ditarik ke akar persoalan, hak atas pangan yang aman dan hak untuk hidup sehat sejatinya adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin oleh negara. Ketika ribuan siswa jatuh sakit akibat makanan yang disediakan oleh program negara, bukankah itu menjadi tanda bahwa ada sesuatu yang keliru dalam sistem perlindungan hak tersebut? Jika negara gagal memastikan mutu, pengawasan, dan keamanan makanan yang ia sediakan sendiri, apakah itu bukan bentuk pelanggaran HAM yang tersembunyi di balik alasan teknis dan administratif? Pertanyaan-pertanyaan ini seharusnya tidak dihindari, sebab justru di sanalah inti dari tanggung jawab negara diuji.
Pemerintah semestinya tidak menjawab permasalahan dengan pembelaan diri, melainkan dengan keterbukaan dan kesediaan untuk memperbaiki. Dalam setiap kebijakan publik yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat, terutama ketika melibatkan anak-anak, yang dibutuhkan bukan sekadar klarifikasi, tetapi juga empati dan tindakan nyata. Menyebut suatu peristiwa sebagai “bukan pelanggaran HAM” tanpa melihat dampak kemanusiaannya justru membuat pemerintah tampak berjarak dari rakyat yang dilayaninya.
Sudah saatnya pemerintah menanggapi kritik bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai cermin. Sebab dari kritik itulah negara bisa bercermin tentang sejauh mana ia benar-benar hadir bagi warganya. Ukuran pemerintahan yang baik tidak ditentukan oleh seberapa piawai ia mengelak dari kesalahan, tetapi oleh seberapa besar keberaniannya untuk mengakui kekeliruan dan memperbaikinya. Pada akhirnya, penghormatan terhadap hak asasi manusia tidak berhenti pada wacana hukum atau pernyataan resmi, melainkan diwujudkan melalui kebijakan yang benar-benar menjamin keselamatan dan martabat manusia.