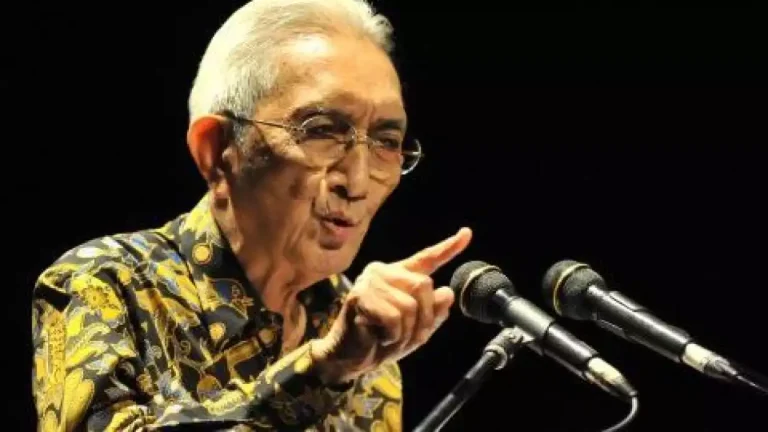ruminews.id – Setiap kali isu pemekaran Provinsi Luwu Raya dibicarakan, yang paling sering muncul ke permukaan adalah soal sejarah, identitas, dan rasa keadilan wilayah. Semua itu sah dan penting. Namun negara, sayangnya, tidak bekerja dengan perasaan saja. Negara bekerja dengan angka, kapasitas, dan daya tahan. Dan ketika seluruh data Luwu Raya diletakkan di atas meja, satu kesimpulan muncul dengan sendirinya yaitu: “Kunci pemekaran Luwu Raya ada pada Luwu Timur.”
Secara ekonomi, Luwu Timur bukan sekadar salah satu kabupaten di Luwu Raya, tapi pusat gravitasinya. Dengan nilai PDRB tahunan yang berada di kisaran Rp30–35 triliun, Luwu Timur menyumbang lebih dari separuh total aktivitas ekonomi seluruh wilayah Luwu Raya yang berada di kisaran Rp55–60 triliun. Ini bukan perdebatan tafsir, tapi hitung-hitungan sederhana. Setiap dua rupiah ekonomi yang bergerak di Luwu Raya, satu rupiahnya berasal dari Luwu Timur. Maka sulit membayangkan provinsi baru yang stabil secara ekonomi tanpa menyertakan wilayah yang menjadi mesin utamanya.
Angka-angka itu menjadi jauh lebih menentukan ketika diterjemahkan ke dalam bahasa fiskal. Provinsi baru tidak hidup dari peta dan logo, tetapi dari Pendapatan Asli Daerah. Dengan struktur ekonomi berbasis industri, energi, dan investasi bernilai tambah tinggi, Luwu Timur memiliki kapasitas fiskal yang nyata. Dengan asumsi konservatif PAD sekitar 15 persen dari PDRB, potensi kontribusi ekonomi Luwu Timur berada di kisaran Rp4,5 hingga Rp5 triliun per tahun. Jika total PAD Provinsi Luwu Raya kelak diproyeksikan sekitar Rp9–10 triliun, maka sekitar separuhnya akan bertumpu pada satu kabupaten ini. Tanpa Luwu Timur, provinsi baru berisiko lahir dengan APBD yang kurus, bergantung pada transfer pusat, dan terbatas ruang geraknya sejak awal.
Di luar fiskal, Luwu Timur juga berfungsi sebagai motor pertumbuhan. Realisasi investasi tahunan yang konsisten di kisaran Rp2–3 triliun menempatkannya sebagai salah satu daerah paling menarik bagi modal di Sulawesi Selatan di luar Makassar. Pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil di atas rata-rata nasional menunjukkan bahwa Luwu Timur bukan hanya mampu bertahan, tetapi mampu menggerakkan. Dalam teori ekonomi wilayah, daerah seperti ini disebut “growth pole”, pusat pertumbuhan yang menarik wilayah sekitarnya untuk ikut naik kelas. Tanpa growth pole, pemekaran hanya memindahkan kantor pemerintahan, bukan menciptakan kemajuan.
Dimensi sosialnya pun tidak bisa diabaikan. Dengan jumlah penduduk sekitar 320–330 ribu jiwa dan mayoritas berada pada usia produktif, Luwu Timur menjadi salah satu penopang demografis Luwu Raya. Lebih dari itu, pengalaman panjang mengelola masyarakat heterogen, industrialisasi, serta relasi kompleks antara negara, korporasi, dan masyarakat memberi Luwu Timur modal sosial dan kapasitas tata kelola yang relatif matang. Ini penting, karena provinsi baru bukan hanya soal ekonomi, tetapi soal stabilitas sosial dan kemampuan mengelola perbedaan.
Jika seluruh fakta ini dirangkai, maka arah diskusinya seharusnya bergeser. Pertanyaannya bukan lagi “apakah Luwu Timur mau ikut pemekaran”, melainkan “apakah pemekaran Luwu Raya masih rasional tanpa Luwu Timur”. Tanpa kabupaten ini, Luwu Raya mungkin bisa lahir secara administratif, tetapi akan kesulitan hidup secara ekonomi. Dengan Luwu Timur, pemekaran memiliki fondasi nyata untuk tumbuh, mandiri, dan berkelanjutan.
Pemekaran wilayah pada akhirnya bukan soal siapa paling keras bersuara, tapi siapa yang paling mampu menopang. Sejarah memberi makna, tetapi ekonomi memberi daya hidup. Dan dalam konteks Luwu Raya hari ini, Luwu Timur bukan sekadar bagian dari cerita pemekaran tapi juga adalah halaman kuncinya. Tanpa halaman itu, ceritanya mungkin tetap dicetak, tetapi sulit dibaca sebagai kisah pembangunan yang masuk akal.
[Erwin]