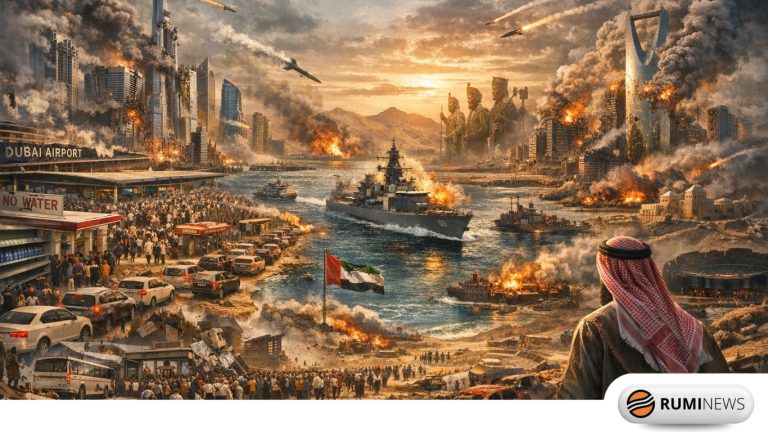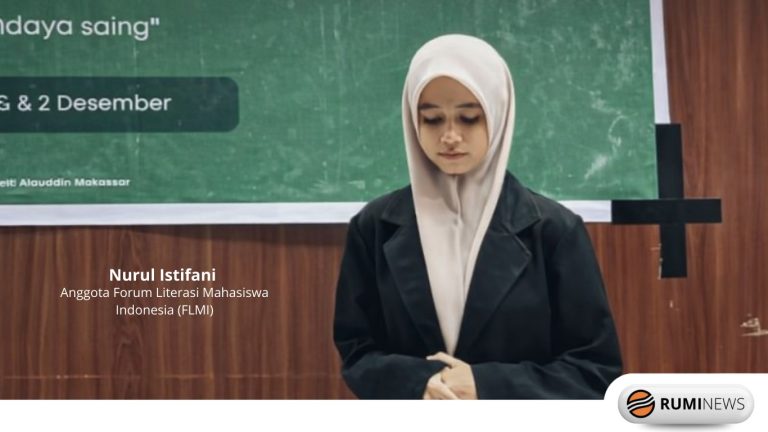ruminews.id – Konsep ekoteologi yang kini mulai digencarkan Kementerian Agama (Kemenag) pada dasarnya lahir dari kegelisahan moral dan spiritual terhadap kerusakan alam yang kian masif. Melalui pendekatan ini, Kemenag berupaya merevitalisasi ajaran agama agar tidak berhenti pada ranah ritual, tetapi mampu menembus dimensi ekologis yang menempatkan alam sebagai bagian dari amanah Tuhan yang harus dijaga. Namun, gagasan ini harus berbenturan dengan realitas bahwa ada satu kekuatan besar dengan gagasan serakahnomics yang juga menggerogoti alam secara amoral mulai dari ujung Kalimantan hingga Maluku Utara. Berdasarkan laporan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), merilis rentetan bencana alam sejak awal Januari 2025 hingga di penghujung December, ada sekitar 2.980 kasus bencana alam di seluruh wilayah Indonesia, dengan jenis bencana alam banjir sebagai kasus terbanyak dengan jumlah 1.489.
Rangkaian bencana tersebut bukan sekadar bencana alam, melainkan momentum untuk merefleksikan kembali atas tugas kita sebagai manusia, apakah kita sebagai penjaga alam, atau pelanggar alam. Kemenag, dengan segala romantisme normatifnya, menegaskan bahwa eksploitasi alam secara destruktif adalah bentuk pengkhianatan terhadap prinsip rahmatan lil ‘alamin. Narasi ekoteologi menuntut manusia untuk menahan diri dari kerakusan, serta mengharmoniskan relasi spiritual dengan lingkungan. Dalam berbagai programnya seperti pengembangan eco-pesantren, literasi lingkungan berbasis agama, dan pendidikan moderasi beragama yang memasukkan aspek etika ekologi. Kemenag menjadikan agama sebagai benteng moral bagi upaya penyelamatan lingkungan.
Namun, apakah etika moral cukup ketika berhadapan dengan logika korporasi yang memiliki kekuasaan ekonomi dan politik ?
Nasr dalam bukunya Man and Nature : The Spiritual Crisis of Modern Man menegaskan bahwa kerusakan lingkungan terjadi karena manusia modern kerap memutus relasi spiritual dengan alam. Alam tidak lagi dianggap sebagai tanda-tanda Tuhan (ayatullah), melainkan sumber material yang harus ditaklukkan.
Di sinilah letak kontestasi antara gagasan ekoteologi Kemenag dan praktik kapitalisme ekstraktif yang dijalankan perusahaan kayu. Korporasi yang kerap berlindung di balik izin legal, seolah menampilkan wajah ramah lingkungan dalam laporan CSR (Corporate Social Responsibility), tetapi realitasnya justru terjadi degradasi hutan, konflik agraria, dan dampak ekologis yang sulit dielakkan.
Berdasarkan laporan dari Greenpeace (2019), Di Kalimantan Tengah, tepatnya hutan di Katingan, Seruyan, dan Kotawaringin Timur telah digerogoti perusahaan kayu sejak awal 2000-an. Ribuan hektar hutan rawa gambut hilang, menyisakan luka ekologis yang menyebabkan kawasan tersebut menjadi episentrum kebakaran hutan 2015 dan 2019. Apakah perusahaan kayu peduli ? Tidak. Yang penting kayu keluar, keuntungan masuk, legalitas aman. Itulah serakahnomics, perhitungan yang hanya mengenal nominal, bukan nilai moral.
Hasil penelitian CIFOR (2006) menunjukkan bahwa fragmentasi lanskap hutan Malinau secara langsung dipicu oleh maraknya izin pemanfaatan hutan skala besar yang diberikan pemerintah daerah setempat. Di Kalimantan Timur, hutan-hutan Malinau dan Kutai Kartanegara yang dulu menjadi benteng keanekaragaman hayati kini tercerai-berai oleh izin IUPHHK dan izin konsesi logging. Efeknya ? Banjir di Samarinda meningkat setiap tahun, sedimen sungai menumpuk, dan masyarakat Dayak harus hidup di antara lahan-lahan gundul yang dulunya menjadi penopang hidup. Tetapi laporan-laporan perusahaan tetap menyebut “operasional berkelanjutan”. Serakahnomics selalu punya kemampuan mencuci dosa melalui jargon keberlanjutan. Di Sulawesi Tengah misalnya, kerusakan hutan di Morowali dan Banggai bukan hanya akibat pertambangan, tetapi juga pembalakan sistematis sejak dua dekade lalu. Lereng-lereng yang gundul kini menjadi titik rawan longsor setiap musim hujan. Menurut laporan Komiu dari kelompok pemantau di Sulteng, selama rentang 2000–2018 Sulawesi Tengah kehilangan hutan alam seluas 559.961,15 hektar. Di beberapa desa, warga harus hidup berdampingan dengan bekas areal tebangan yang tidak pernah dipulihkan. Belakangan justru terjadi di Pulau Sumatera.
Semua kerusakan ini memperlihatkan satu hal bahwa ekoteologi dan serakahnomics adalah dua gagasan yang bersebrrangan dan tidak akan pernah bersatu. Jika ekoteologi berbasis pada nilai moral, kesadaran spiritual, dan penghormatan terhadap ciptaan Tuhan. Sebaliknya, serakahnomics berbasis keserakahan, akumulasi, dan manipulasi legalitas.
Masalahnya, apakah Kemenag berani menjadikan ekoteologi sebagai kritik struktural terhadap negara dan korporasi ? atau ekoteologi hanya akan berakhir sebagai wacana lembut yang disampaikan dalam seminar, tanpa pernah mengusik akar ekonomi ekstraktif yang menghancurkan bumi ? Kemenag kerap berbicara tentang rahmatan lil ‘alamin, tetapi hutan yang menjadi “alam” itu sedang sekarat. Korporasi kayu yang hidup dari logika serakahnomics tidak peduli pada ayat-ayat ekologis dalam Al-Qur’an. Mereka hanya peduli pada harga kayu meranti, ulin, agathis, dan sengon di pasar global.
Kemenag perlu mengakui bahwa ekoteologi tidak boleh berjalan sendirian dalam ruang-ruang seminar yang elitis. Sudah saatnya ecorangers Kemenag berjumpa dengan realitas, korporasi yang rakus, pemerintah daerah yang oportunis, aparat yang kompromistis, dan masyarakat yang terhimpit ketiak penguasa. Jika tidak, ekoteologi hanya menjadi jargon spiritual yang diperdagangkan pada forum-forum resmi.
Ekoteologi, bila dipahami secara serius, justru membawa konsekuensi radikal, yaitu menempatkan alam bukan sekadar sumber daya, tetapi subjek yang memiliki nilai intrinsik. Artinya, setiap kerusakan hutan, perampasan lahan, atau hilangnya keanekaragaman hayati merupakan pelanggaran moral yang seharusnya menghasilkan seruan profetis, yaitu suara keagamaan yang menyalahkan ketidakadilan ekologis. Dalam tradisi agama-agama, terutama Islam, peran para Nabi bukan hanya membimbing ibadah, tetapi mengkritik struktur ekonomi dan politik yang zalim. Mengapa Kemenag tidak mengambil posisi ini ?
Kemenag harus lebih berani. Ekoteologi tidak boleh berhenti pada narasi, tetapi paling tidak dapat diwujudkan dalam tiga langkah : pertama, memperkuat jejaring dengan masyarakat adat dan kelompok lingkungan; kedua, memberikan pelatihan advokasi ekologi kepada penyuluh agama agar mereka bisa menjadi agen perubahan di daerah masing-masing; ketiga, menuntut transparansi dan pemantauan ketat terhadap perusahaan tambang kayu yang mengancam keberlanjutan ekosistem.
Tanpa keberanian struktural ini, ekoteologi hanya akan menjadi doa hampa yang tidak mampu menghentikan deru mesin penggundul hutan. Jika Kemenag hanya berani bicara tentang perlunya mencintai alam tanpa berani menantang serakahnomics, maka ia hanya menjadi ornamen spiritual yang tidak relevan dengan krisis zaman. Sebab yang kita hadapi bukan hanya krisis ekologis, tetapi sistem ekonomi yang menjadikan kerusakan sebagai model bisnis.
Pada akhirnya, Hutan akan hilang, Sungai akan mati, Masyarakat adat akan tergusur, dan ekoteologi hanya akan menjadi suara lirih yang kalah oleh bunyi mesin penebang.