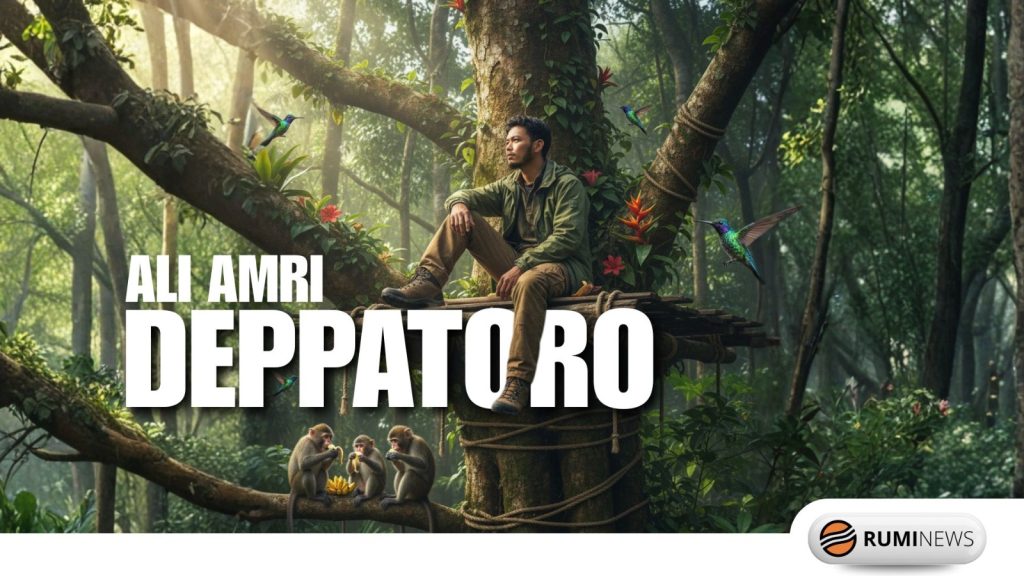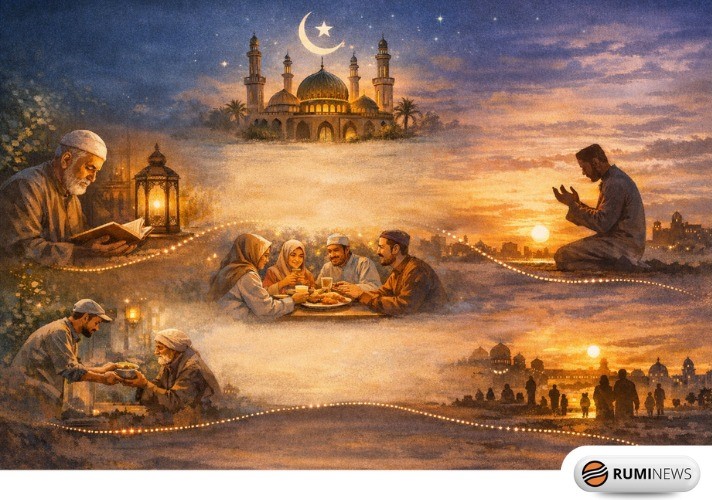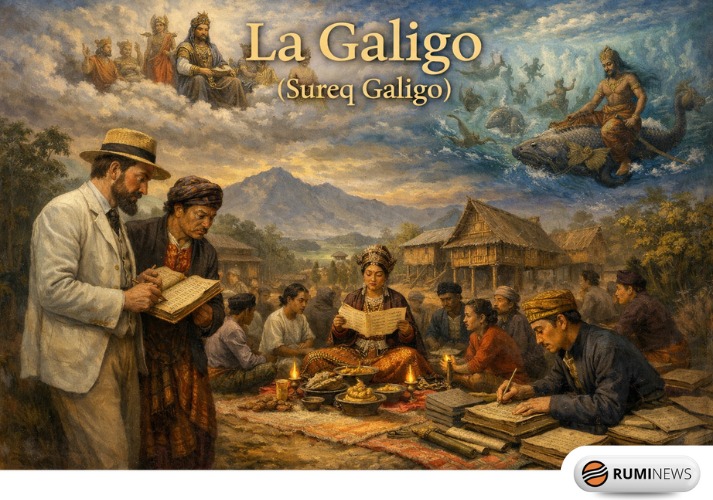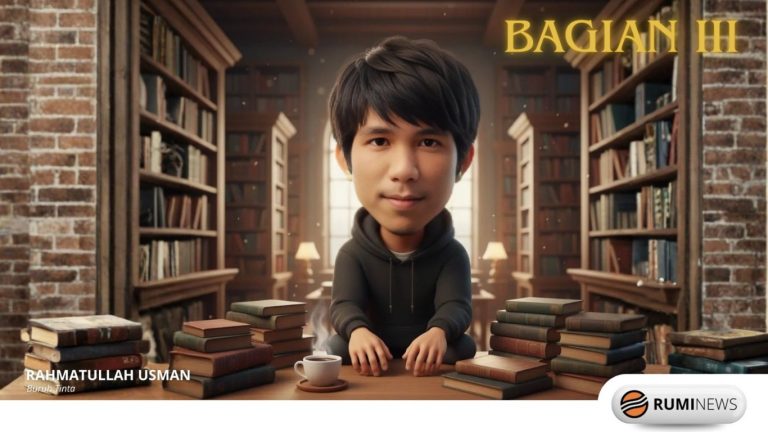ruminews.id – Dalam sejarah politik Indonesia, setiap rezim selalu memiliki gaya tutur sendiri yang direfleksikan sebagaisebuah cara berbicara sekaligus menjadi cermin daribagaimana kekuasaan merekonstruksi makna. Era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkanhal serupa.
Sejak awal masa jabatannya, publik disuguhi bahasayang tegas, militeristik, dan penuh metafora perjuangan. Kata-kata seperti “kedaulatan”, “kemandirian”, dan“percepatan pembangunan” kini menjadi diksi yang berulang dalam berbagai pidato kenegaraan (Setneg, 2025). Dalam pidatonya pada Mei 2025, Prabowomenegaskan bahwa “energi dan pangan adalah kuncikedaulatan bangsa.”
Bahasa semacam ini tentu tidaklah netral. Ia menjelmamenjadi sebuah strategi kekuasaan simbolik. Jikameminjam istilah Pierre Bourdieu (1991), maka iaberfungsi sebagai “tindakan simbolik yang implikatif danmengatur legitimasi sosial.” Melalui bahasa, kekuasaantidak hanya berbicara, tetapi juga mendisiplinkan carabagaimana publik memahami kenyataan.
Bahasa sebagai Alat Legitimasi Kekuasaan
Bahasa kekuasaan pada masa kini bekerja bukanmelalui perintah keras, tetapi melalui pembingkaianmakna (reframing) yang halus. Dalam berbagai forum, istilah “ketahanan pangan” atau “kemandirian bangsa” digunakan bukan hanya untuk menjelaskan kebijakanekonomi, tetapi juga untuk meneguhkan ideologipertahanan. Dalam konteks ini, ekonomi ditempatkan di bawah narasi nasionalisme—seolah-olah keberhasilanekonomi adalah bukti loyalitas kepada negara (Setneg, 2025).
Bagi Norman Fairclough (1995), wacana politik selaluberfungsi membentuk kesadaran melalui naturalisasiideologi; apa yang ideologis, disajikan sebagai hal yang “alami”. Ketika kata “kedaulatan” dilekatkan pada hampirsemua kebijakan publik, makna politiknya bergeser: iabukan lagi sekadar soal kemandirian negara, melainkanalat untuk mengamankan keabsahan kekuasaan. Kritikterhadap kebijakan semacam itu pun dapat denganmudah dipersepsikan sebagai serangan terhadap“kedaulatan bangsa”.
Retorika Nasionalisme dan Moralitas Negara
Bahasa nasionalisme di era ini dibungkus denganmoralitas. Kata-kata seperti “pengabdian”, “loyalitas”, dan“cinta tanah air” kerap muncul beriringan dengan frasa“percepatan pembangunan”. Retorika ini menciptakankesan bahwa percepatan adalah kewajiban moral, danmenunda atau mengkritik berarti tidak nasionalis ataubahkan kontra-produktif.
Prabowo dalam beberapa pidatonya seringmenggunakan bentuk inklusif seperti “kita harus terusberjuang” atau “kita berada di jalan yang benar.”
Diksi “kita” di sini bekerja secara pragmatis sebagaimetafora kebersamaan, tetapi pada saat yang samamenciptakan garis batas; siapa yang tidak termasukdalam “kita”, secara simbolik menjadi “mereka” pihak yang dianggap tidak sejalan dengan semangat bangsa.
Foucault (1972) menyebut mekanisme semacam inisebagai “rezim kebenaran”, yaitu sistem ujaran yang menentukan siapa yang boleh berbicara dan dengan caraseperti apa. Dengan demikian, bahasa nasionalismeberubah menjadi perangkat moral yang menilai kepatuhanwarganya.
Bahasa Pembungkaman dan Kontrol
Jika pemerintahan sebelumnya sering menggunakanistilah “radikal” dan “intoleran” untuk meredam oposisi, maka pada era ini pembungkaman hadir dalam wajah baru melalui diksi seperti “stabilitas nasional”, “penegakan hukum”, dan “tindak tegas terhadapprovokator digital.”
Kementerian dan aparat keamanan seringmenegaskan pentingnya menjaga stabilitas di tengahkebebasan digital (Setneg, 2025). Bahasa hukum dankeamanan ini tampak netral, namun secara pragmatik iaberfungsi mengendalikan ruang ujaran publik.
Kasus gugatan Menteri Pertanian Andi AmranSulaiman terhadap Tempo Inti Media Tbk adalah cerminyang nyata. Gugatan senilai lebih dari Rp 200 miliar atasberita “Poles-Poles Beras Busuk” (Tempo.co, 2025) dinilaiLBH Pers sebagai bentuk yang berpotensi membungkamkritik, meski media tersebut telah mengikuti mekanismehak jawab Dewan Pers.
Dalam analisis wacana, tindakan seperti inimenunjukkan bahwa kekuasaan tidak perlu menutupmulut lawan bicara; cukup mengubah makna bicara itusendiri. Kritik kemudian dikonstruksi sebagai “gangguanterhadap stabilitas”, bukan sebagai bagian dari demokrasi.
Normalisasi Kekuasaan dalam Komunikasi Publik
Bahasa kekuasaan juga mengatur nada bicara publikmelalui konsep “kritik konstruktif”. Di permukaan, istilah initerdengar positif mengajak warga untuk memberimasukan yang “produktif”. Namun di baliknya tersembunyimekanisme penyaringan: kritik yang tidak sesuai dengankerangka “konstruktif” akan mudah dilabeli sebagai “tidakmembantu bangsa”.
Fenomena ini memperlihatkan bagaimana kekuasaanmenormalisasi bahasa. Masyarakat sipil seolah diberistimulus agar menyesuaikan gaya berujar agar selarasdengan diksi resmi yang dibangun oleh kekuasan secaratunggal.. secara implisit, masyarakat sipil digiring untukberhati-hati, memilih kata yang aman, dan menjagaintonasi agar tetap “sopan terhadap negara”.
Fairclough (2001) menyebut proses semacam inisebagai “kolonialisasi kesadaran linguistik” ketikamasyarakat secara sukarela meniru bahasa kekuasaankarena takut dipidana atau kehilangan legitimasi sosial. Maka, bahasa tidak lagi menjadi alat komunikasihorizontal, tetapi mekanisme vertikal yang menandai siapayang berhak berbicara.
Refleksi dan Penutup
Bahasa dalam rezim ini memperlihatkan paradox; di satu sisi ia menjanjikan keterbukaan dan solidaritas, di sisilain ia menertibkan perbedaan dan kritik. Diksi-diksiseperti “kedaulatan”, “percepatan”, “stabilitas nasional”, dan “konstruktif” membentuk lanskap wacana yang tampak patriotik, namun menyimpan potensipembungkaman.
Jika Orde Baru menekan dengan larangan eksplisit, maka era kini menggunakan persuasi linguistik menundukkan dengan kata-kata yang terdengar bijak.
Seperti diingatkan Fairclough (1992), analisis wacanakritis bukan hanya membaca teks, tetapi membaca relasikekuasaan di balik teks. Dalam konteks Indonesia kini, setiap kata politik membawa jejak ideologinya sendiri. Maka, tugas akademisi bukan sekadar menilai apakahbahasa itu santun atau kasar, melainkan menelusuribagaimana ia bekerja sebagai instrumen kontrol sosial.Sebab di balik kata “kedaulatan” bisa tersembunyi bentukbaru penaklukan, dan di balik kata “konstruktif” bisabersemayam keheningan yang dipaksakan.
Daftar Rujukan Singkat
Bourdieu, P. (1991). Language and Symbolic Power. Polity Press.
Fairclough, N. (1992). Discourse and Social Change. Polity Press.
Fairclough, N. (1995). Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language. Longman.
Fairclough, N. (2001). Language and Power (2nd ed.). Pearson.
Foucault, M. (1972). The Archaeology of Knowledge. Routledge.
LBH Pers. (2025). Pernyataan sikap atas gugatan MenteriPertanian terhadap Tempo Inti Media Tbk.
Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2025). PidatoPresiden Prabowo Subianto tentang Kedaulatan Energidan Pangan.