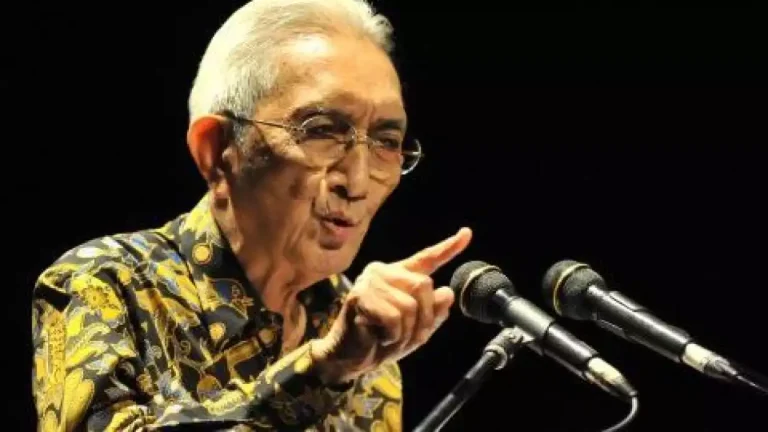ruminews.id – Bayangkan jika Rousseau sang pencetus “Kontrak Sosial” bangkit dari kuburnya dan membaca laporan evaluasi CELIOS. Saat mengetahui nilai rata-rata pemerintahan Prabowo-Gibran cuma 3 dari 10, saya yakin dia akan menjerit dalam bahasa Prancis: “C’est une farce!”. Ini lelucon! Kontrak sosial yang ia bayangkan sebagai perjanjian suci antara penguasa dan rakyat, di Indonesia ternyata lebih mirip kontrak fiktif ber-plot twist: rakyat menepati janji dengan membayar pajak dan taat aturan, sementara penguasa membalasnya dengan kebijakan yang 80% dinilai tak sesuai kebutuhan publik. Ibarat drama, ini bukan lagi “Romeo dan Juliet” tapi “Prabowo dan Gibran: The Comedy of Errors”.
Kita mulai dari krisis legitimasi yang menggelikan. Max Weber pasti tertawa getir melihat pemerintahan yang unggul dalam karisma pencitraan tapi gagal total dalam kinerja substantif. Bagaimana mungkin sebuah pemerintah yang gemar tampil di media justru dinilai 91% publik gagal berkomunikasi? Mereka seperti influencer yang sibuk membuat konten viral tapi lupa bahwa produk yang dijualnya cacat. Sementara 63% publik mencium bau militeristik dalam tata kelola negara, seolah-olah demokrasi kita sedang diubah menjadi barak militer dimana kebebasan sipil adalah desertir yang harus dikekang.
Lalu ada lelucon ekonomi yang lebih absurd lagi. Adam Smith pasti berguling-guling di kuburnya menyaksikan “tangan tak terlihat” versi Indonesia. Bukan tangan yang mengatur pasar, tapi tangan yang tidak tampak saat rakyat menjerit akibat 84% merasa pajak memberatkan. Padahal dalam filosofi kontrak sosial, pajak seharusnya seperti iuran bersama untuk pesta rakyat. Nyatanya? 53% masyarakat merasa tak mendapat secuil pun kue dari pesta itu. Program Makanan Bergizi Gratis pimpinan Dadan Hindayana malah berubah menjadi program “makanan bergizi plus bonus keracunan”. Ini bukan kebijakan publik, tapi eksperimen gastronomi yang gagal!
Kita sampai pada tragedi para menteri yang membuat Plato menangis di alam baka. Dalam “Republic”, ia memimpikan negara dipimpin raja-filsuf yang bijaksana. Tapi di negeri kita, kita menyaksikan 10 menteri dengan nilai minus menggurita. Ada Bahli Lahadalia yang kebijakan energinya dinilai minus 151, seakan-akan dia memimpin ESDM dengan prinsip “biarkan gelap yang penting saya tetap bercahaya”. Ada Natalius Pigai di HAM yang kinerjanya minus 79, seolah-olah HAM adalah hak asasi yang harus diasingkan. Mereka seperti sopir bus buta arah yang menyetir bus bernama Indonesia dengan 270 juta penumpang, sambil menyalahkan penumpang yang mabuk akibat gaya nyetirnya.
Yang lebih menggelikan adalah respon pemerintah terhadap semua kritik ini. Alih-alih introspeksi, yang terjadi justru defensif dan denial. Padahal data berbicara jelas, 96% publik minta reshuffle, 98% setuju pemangkasan nomenklatur. Ini bukan sekadar ganti menteri, tapi semacam “revolusi administratif” dimana kita perlu membersihkan kabinet dari para pelawak yang menyamar sebagai negarawan.
Konfusius pernah berkata bijak, “Dalam negara yang benar, yang penting adalah kepercayaan rakyat.” Kini kepercayaan itu menguap bagai asap di angin. Elektabilitas Prabowo turun 34% dari pemilihnya sendiri, sebuah koreksi demokrasi yang nyaring. Ini adalah alarm yang berisik: jika kinerja tidak berubah, kontrak sosial bukan hanya retak, tapi akan hancur menjadi debu.
Mungkin kita perlu mengutip Woody Allen dengan sedikit modifikasi: “Aku tidak takut pada kegagalan pemerintah, aku takut pada ketidakpedulian mereka terhadap kegagalan itu sendiri.” Laporan CELIOS ini adalah cermin besar di depan wajah kekuasaan. Dan di depan cermin itu, pemerintah berdiri dengan pakaian kebesaran baru, sementara rakyat yang melihatnya justru berteriak lantang: “Kaisarnya telanjang!”
(Catatan; Esai ini adalah satire yang ditulis berdasarkan data yang ada dalam laporan CELIOS, meski disajikan dengan bumbu jenaka untuk menggugah nalar dan memicu diskusi kritis. Karena kadang, untuk memahami tragedi, kita perlu menertawakannya dulu).