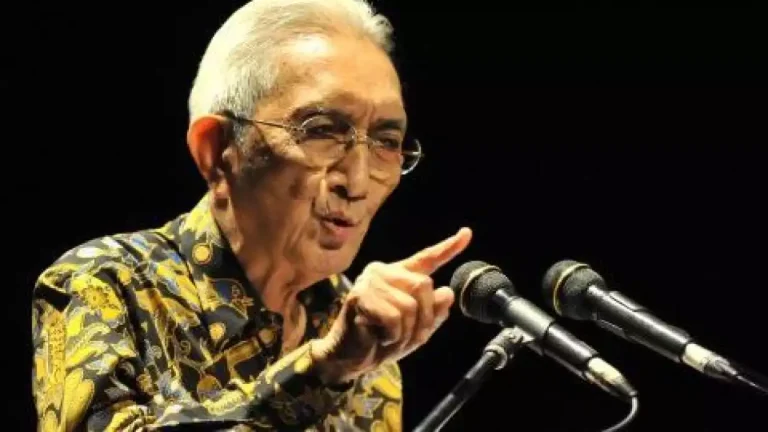ruminews.id – Langit jagat maya kembali bergemuruh. Tagar #BoikotTrans7 berputar cepat, seperti badai yang lahir dari amarah dan cinta yang tak sempat menimbang. Sebuah tayangan tentang kehidupan pesantren dianggap menghina, menodai, bahkan menista. Maka seruan boikot menjadi mantra, dan kritik pun dianggap dosa.
Namun di balik riuh itu, kita lupa: pesantren bukanlah kaca yang tak boleh berdebu. Ia adalah lembaga mulia yang hidup dalam denyut masyarakat, tempat ilmu dan akhlak bersemayam, tetapi juga tempat manusia bernafas dan di sanalah, kadang, kekeliruan menemukan ruangnya.
Apakah kita lupa pada berita tentang dugaan korupsi sang mantan menteri agama, yang justru lahir dari rahim yang sama bernama keagamaan? Atau tangis santri perempuan yang disembunyikan di balik pagar tinggi, korban pelecehan oleh mereka yang seharusnya menjaga? Dan bagaimana dengan bangunan pesantren yang ambruk, bukan karena hujan deras, melainkan karena fondasi yang rapuh oleh kelalaian dan kepentingan?
Kita terlalu sibuk membungkus luka dengan klaim kehormatan.
Kita terlalu cepat tersinggung, sebelum sempat bercermin.
Kita marah pada televisi, tapi lupa memarahi realitas.
Kita hidup di zaman ketika budaya pesantren dipaksa dinormalisasi, seolah semua yang lahir dari balik temboknya adalah suci dan tak tersentuh cela. Kritik dianggap judgmental, dan keberanian menyoal dianggap melecehkan agama. Padahal, televisi, media sosial, hingga parodi para influencer hanyalah cermin dari keresahan yang sesungguhnya keresahan melihat para petinggi pesantren yang menjauh dari ajaran Islam yang mereka serukan.
Kita menyaksikan bagaimana air doa dijual seperti komoditas, air celupan jari dijadikan berkah berbayar, kuburan palsu dipuja-puja seolah jalan pintas menuju surga. Ada pula yang menjual barang yang diklaim peninggalan Rasulullah, bahkan rambut sang Nabi, untuk keuntungan pribadi. Di sudut lain, tampak santri bersikap berlebihan mencium tangan hingga batas yang memalukan, jongkok ketika petinggi pondok lewat, bahkan berebut makanan yang ditendang pengurusnya, dan merangkak ketika diberi nasi bungkus.
Semuanya dibungkus dengan label “ta’dzim” padahal itu seringkali bukan penghormatan, melainkan perendahan martabat.
Lebih getir lagi, ketika sebagian ustaz berbicara hal tak senonoh di mimbar yang mestinya suci. Lelucon cabul disamarkan sebagai dakwah, dan kritik atas kelakuan itu malah dianggap serangan terhadap Islam. Lalu masyarakat yang memberi fakta, yang menyuarakan kegelisahan, justru diserbu balik dengan dalih: “Kamu tak paham kehidupan pesantren.”
Feodalisme dalam pesantren apakah benar itu fitnah, atau justru cermin kecil dari kebisuan yang kita pelihara? Tidak semua pesantren demikian, benar. Tapi bukankah menutup mata pada segelintir kebusukan sama saja dengan membiarkannya tumbuh?
Mahasiswa Nahdlatul Ulama, para alumni santri, dan mereka yang mencintai pesantren tentu berhak marah. Tapi marah yang luhur bukan marah yang membungkam, melainkan marah yang menuntut perbaikan. Karena cinta sejati bukan hanya memuja, tapi juga berani mengoreksi.
Seakan-akan kita harus memaklumi semua kejanggalan atas nama budaya. Seakan-akan kebodohan harus dirawat agar disebut adab.
Padahal, adab sejati bukan tunduk tanpa nalar, bukan hormat yang membungkam.
Pesantren bukan menara gading yang steril dari kritik ia adalah taman ilmu yang harus tumbuh bersama kejujuran.
Lalu mengapa ketika cermin menampakkan noda, kita malah memecahkannya?
Tagar boikot boleh menggema, tapi jangan sampai ia menenggelamkan nurani.
Sebab lebih berbahaya dari fitnah media adalah diam yang mengafirmasi kesesatan.
Dan cinta yang sejati pada pesantren bukanlah yang menutup mata atas luka-lukanya, melainkan yang berani membersihkannya dengan ilmu, keberanian, dan kejujuran.
Mungkin Trans7 keliru dalam cara menarasikan, tapi lebih keliru lagi bila kita menolak bercermin.
Sebab pesantren bukan hanya warisan masa lalu ia adalah amanah masa depan.
Dan masa depan itu tak akan bersinar bila kita terus memoles cermin retak dengan pujian semu.