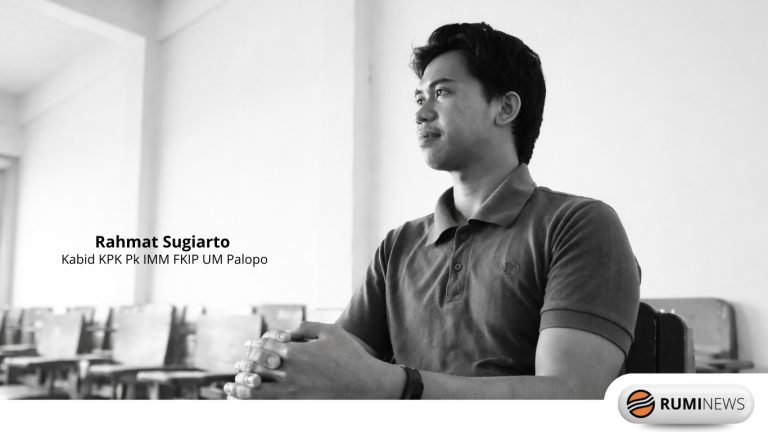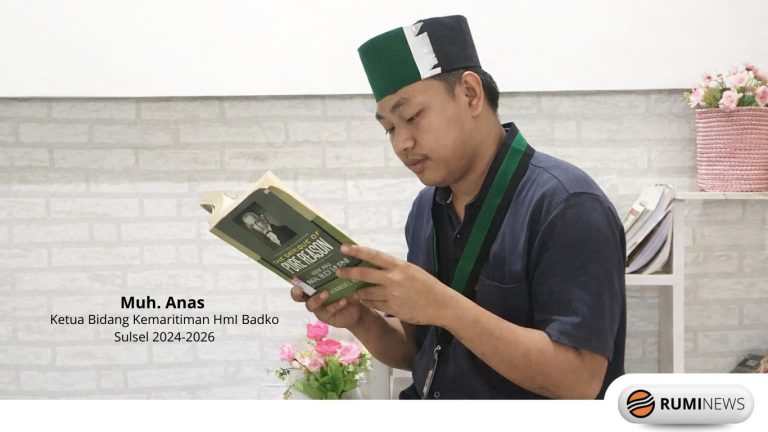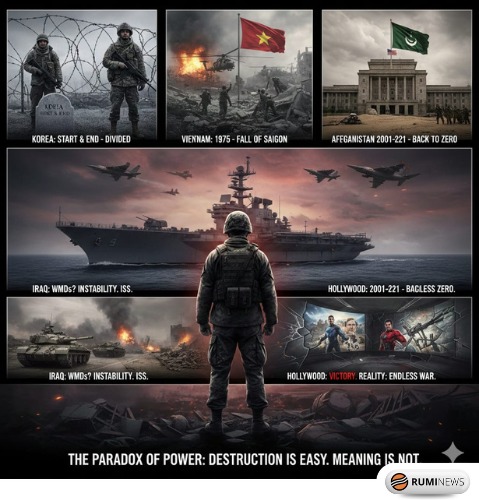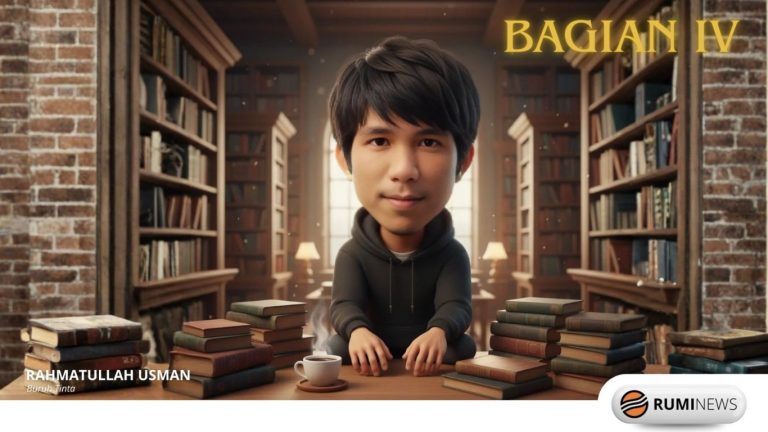ruminews.id, Jakarta – Akhir-akhir ini, publik terus menyoroti persoalan pertambangan. Kehadiran tambang masih dipertanyakan, apakah sekadar ambisi investasi, pertumbuhan ekonomi, atau justru gelombang ketidakjelasan bagi masyarakat lokal. Tentu, keberlangsungan lingkungan dan hajat hidup masyarakat (kesehatan dan kesejahteraan) harus menjadi perhatian utama ketika tambang hadir. Undang-Undang tambang Nomor 40 Tahun 2017 dan Undang-Undang Cipta Kerja menegaskan bahwa setiap kegiatan pertambangan wajib melalui Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai syarat utama sebelum izin usaha pertambangan dikeluarkan.
Dua Sisi Kehadiran Tambang
Kehadiran tambang kerap diibaratkan sebagai dua sisi mata uang. Pada satu sisi, tambang berkontribusi pada penerimaan dan pendapatan negara. Namun di sisi lain, ia membawa kerugian jangka panjang yang bahkan dapat menghadirkan ancaman kematian, baik dari segi lingkungan maupun sosial.
Laporan Menteri ESDM tahun 2024 menunjukkan sektor mineral dan batu bara menyumbang Rp140,66 triliun, atau 52% dari seluruh penerimaan sektor energi dan sumber daya alam. Namun, penerimaan tersebut tidak sebanding dengan kerugian fiskal, kerugian ekonomi lokal, kerugian lingkungan, serta dampak sosial dan kesehatan yang ditimbulkan. Yang tidak kalah penting adalah perhatian terhadap kelestarian lingkungan dan kehidupan masyarakat sekitar.
Data Jaringan Advokasi Tambang (JATAM, 2022) mencatat lebih dari 3,1 juta hektare lahan produktif di Kalimantan berubah menjadi area tambang. Kehadiran tambang sering memicu konflik sosial, sekaligus menyingkirkan lahan produktif yang selama puluhan tahun menjadi sumber ekonomi lokal.
Tambang memicu banjir, polusi udara, serta pencemaran air dan tanah. Dengan izin investasi yang kerap diberikan begitu mudah, dikhawatirkan hak-hak masyarakat sekitar tambang terabaikan. Perusahaan tambang seringkali hanya menikmati keuntungan, lalu meninggalkan wilayah yang sudah rusak. Sementara itu, masyarakat setempat harus hidup dengan tanah tidak produktif, kehilangan mata pencaharian, dan berhadapan dengan kemiskinan ekstrem.
Ancaman Terhadap Ekosistem Laut dan Nelayan
Kehadiran tambang juga menjadi ancaman bagi nelayan. Tanpa adanya AMDAL yang serius, limbah tambang kerap dialirkan ke kawasan yang tidak semestinya, sehingga mencemari laut dan mengubah ekosistem. Akibatnya, nelayan terpaksa melaut lebih jauh dan mengeluarkan biaya operasional lebih besar. Studi Auriga Nusantara (2023) mengungkapkan bahwa aktivitas tambang di Mimika telah mengurangi area tangkapan ikan tradisional hingga 35% dalam satu dekade terakhir. Nelayan yang sebelumnya bisa mendapat hasil tangkapan 20–25 kg/hari, kini hanya memperoleh 7–20 kg/hari. Kerugian ekonomi nelayan tradisional di Mimika diperkirakan mencapai Rp72 miliar per tahun.
Setiap perusahaan tambang kerap menjanjikan penyerapan tenaga kerja lokal sebagai strategi menarik simpati masyarakat. Namun kenyataan berbeda. Data Kementerian ESDM (2022) menunjukkan hanya 30–35% tenaga kerja di sektor tambang yang berasal dari masyarakat lokal, itu pun sebagian besar hanya dipekerjakan sebagai buruh kasar dengan upah rendah. Kehadiran tambang justru membuat masyarakat lokal kehilangan tanah, menghadapi ancaman banjir, hingga hidup dalam bayang-bayang kerusakan lingkungan.
Ironi Kemiskinan di Daerah Tambang
Meski menjanjikan pertumbuhan ekonomi, kenyataan di lapangan menunjukkan hal yang berbeda. Contohnya di Papua, tingkat kemiskinan di sekitar area tambang pada tahun 2023 tercatat 27,5%, jauh di atas angka rata-rata nasional 9,36%. Hal serupa juga terjadi di Kalimantan Timur, meski menjadi lumbung batu bara nasional, 11% penduduknya masih hidup di bawah garis kemiskinan.
Di Morowali, Sulawesi Tengah, ketimpangan semakin tajam dengan indeks gini ratio mencapai 0,41 akibat dominasi industri tambang. Fakta ini memperlihatkan bahwa klaim kesejahteraan dari tambang tidak pernah benar-benar terwujud.
Kerangka hukum pertambangan di Indonesia terus mengalami perubahan. UU No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba sempat memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Namun, UU No. 23 Tahun 2014 kemudian menarik kewenangan tersebut ke tingkat provinsi. Terbaru, UU No. 6 Tahun 2023 (Omnibus Law Cipta Kerja) menyatakan adanya sentralisasi izin melalui OSS (Online Single Submission), namun daerah tetap dilibatkan dalam aspek rekomendasi teknis dan pengawasan.
Meski tidak lagi berwenang dalam penerbitan izin, pemerintah daerah masih memiliki peran penting dalam memberikan rekomendasi tata ruang, mitigasi dampak lingkungan, serta pengawasan aktivitas tambang yang ada di wilayahnya.
Komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan menuntut keberanian kepala daerah. Pemerintah daerah harus berani menggunakan haknya untuk merekomendasikan agar wilayahnya tidak ditetapkan sebagai Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP). Hal ini penting demi menjaga keberlanjutan ekologi sekaligus melindungi mata pencaharian masyarakat lokal.
Pertanyaannya, apakah kita akan terus mengulang pola yang sama dan mewariskan kerusakan bagi anak cucu kita? Ataukah kita memilih jalan keberanian untuk berkata : Tambang bukanlah pilihan, keberlanjutanlah jawaban.
Oleh : Fitra ( (Peneliti Prolog Initiative)