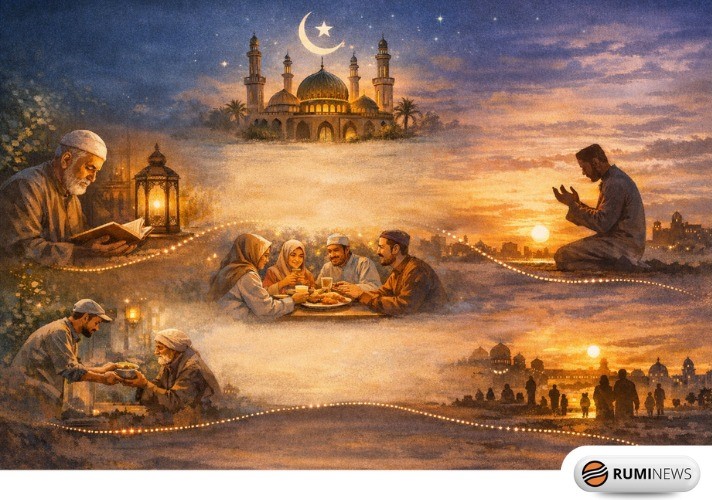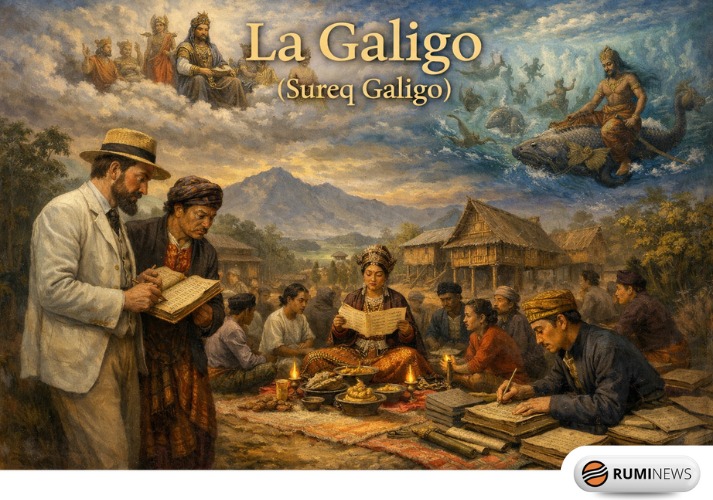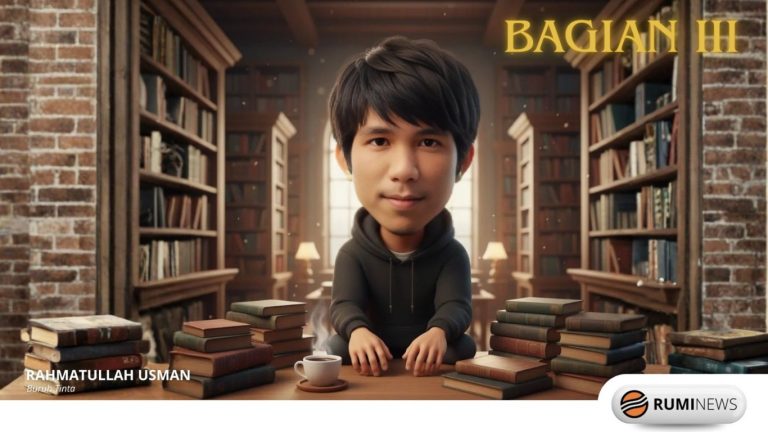Pergantian Menteri Keuangan dari Sri Mulyani Indrawati ke Purbaya Yudhi Sadewa memunculkan perdebatan baru tentang arah kebijakan fiskal dan moneter. Salah satu langkah awal yang menimbulkan sorotan adalah rencana Purbaya memindahkan sekitar Rp200 triliun dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) ke bank umum dengan skema deposito berbunga komersial 4,5 persen.
Sri Mulyani vs Purbaya: Dua Pendekatan
Sri Mulyani selama ini menempatkan SAL di Bank Indonesia (BI) untuk mendukung stabilitas fiskal melalui operasi moneter dan pengendalian yield Surat Berharga Negara (SBN). Sebaliknya, Purbaya memilih menaruh SAL di bank umum dengan logika bahwa bunga 4,5 persen akan menjadi cost of fund bagi bank. Bank, pada gilirannya, diyakini akan menyalurkan kredit ke sektor riil dengan bunga 6–7 persen, setara kupon SBN.
Di titik inilah perbedaan mazhab muncul. Jokowi pernah menyebut Purbaya berbeda aliran dengan SMI. Namun faktanya, keduanya tetap berangkat dari keyakinan pada mekanisme pasar, hanya berbeda pada cara menyalurkan likuiditas—apakah lewat instrumen moneter (SMI) atau lewat perbankan (Purbaya).
Debat Mazhab: Keynesian vs Monetaris
Menurut perspektif Keynesian, likuiditas berlebih justru bisa mendorong spekulasi ketika ekonomi sedang dalam gejolak. Inilah yang dulu menjadi dasar burden sharing saat pandemi Covid-19, ketika BI membeli SBN pemerintah di pasar perdana untuk membiayai defisit. Tujuannya jelas: mengarahkan likuiditas ke fiskal untuk menopang belanja publik.
Sebaliknya, pandangan monetaris ala Milton Friedman percaya bahwa mekanisme bunga akan menyeimbangkan pasar. Jika bunga simpanan cukup menarik, bank akan terdorong menyalurkan kredit. Namun, pertanyaan besarnya: apakah benar ada permintaan kredit yang sehat dan mampu membayar bunga 6–7 persen dalam situasi ekonomi sekarang?
Problem Transmisi Kredit
Purbaya tampaknya terlalu percaya pada asumsi bahwa bank akan otomatis menyalurkan kredit. Padahal, bank bekerja berdasarkan logika risk and return. Jika risiko gagal bayar tinggi, sekalipun dana tersedia dengan bunga murah, kredit tidak akan mengalir.
Lebih jauh, penempatan SAL dalam bentuk deposito on call berarti dana bisa diambil pemerintah sewaktu-waktu. Bagi bank, ini bukan aset likuid yang bisa dengan aman dipinjamkan untuk kredit jangka menengah atau panjang. Risiko mismatch likuiditas sangat besar, mirip dengan pengalaman BMPK (Batas Maksimum Pemberian Kredit) era Orde Baru yang berujung pada kredit macet.
Belajar dari QE AS dan China
Kebijakan Purbaya juga dibandingkan dengan praktik Quantitative Easing (QE) pasca-krisis finansial 2008. Di AS, The Fed membeli aset keuangan dan menyalurkan dana lewat perbankan, namun tetap dengan government arm berupa ekspansi fiskal—misalnya subsidi pengangguran dan insentif sektor riil. Transmisi tidak diserahkan sepenuhnya ke mekanisme pasar.
China berbeda lagi: devisa dikelola ketat, seluruh hasil ekspor harus masuk sistem perbankan domestik. Aliran dana diarahkan langsung ke sektor riil dengan kontrol pemerintah. Kedua model ini menunjukkan satu hal: kredit hanya akan jalan bila ada intervensi negara ke sektor riil, bukan sekadar bunga simpanan.
Kunci di Sektor Riil, Bukan di Bank
Kritik utama pada gagasan Purbaya adalah ia menaruh beban terlalu besar pada perbankan. Padahal, peran Menkeu seharusnya adalah memoderasi kebijakan agar Quick Win sektor riil yang dirancang kementerian teknis bisa berjalan. Tanpa perlindungan industri domestik—seperti kasus keterlambatan Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD) di sektor tekstil—tidak ada insentif bagi dunia usaha untuk mengambil kredit, sekalipun bunga rendah.
Contoh lain, di sektor pangan biaya produksi gabah on farm di Indonesia adalah yang tertinggi di kawasan. Tanpa reformasi biaya lahan dan efisiensi produksi, menaruh SAL di bank tidak akan mengubah struktur ongkos, dan impor tetap lebih murah untuk menjaga inflasi.
Kesimpulan: Antara Mazhab dan Realitas
Purbaya mungkin ingin tampil sebagai true believer of market mechanism. Namun kebijakan menaruh SAL di bank umum berisiko hanya menjadi “emak-emak ekonomi”—sekadar memindahkan dana ke tempat dengan bunga lebih tinggi tanpa strategi jelas ke sektor riil.
Sejarah akan membuktikan apakah Rp200 triliun SAL benar-benar menjadi tongkat Nabi Musa yang mampu membelah lautan problem ekonomi, atau hanya sekadar eksperimen yang kembali menegaskan bahwa tanpa reformasi struktural di sektor riil, likuiditas akan tetap mengendap sebagai uang murah yang tidak produktif.