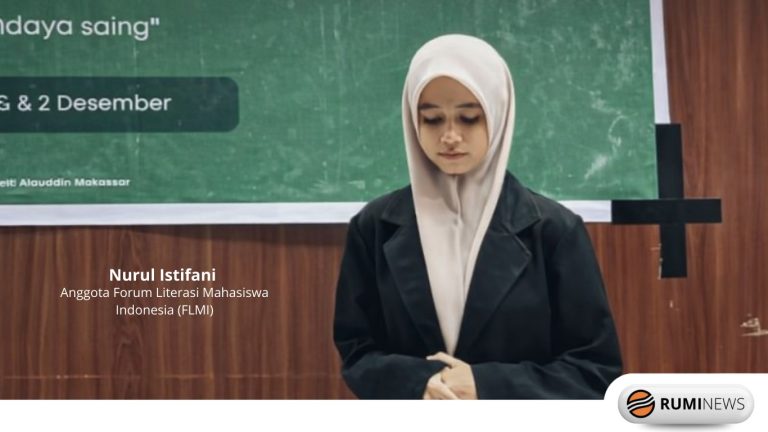ruminews.id – Kekerasan seksual terhadap perempuan masih terus terjadi. Kita sering membacanya sebagai berita singkat, lalu melupakannya esok hari. Padahal bagi korban, peristiwa itu tidak pernah benar-benar selesai. Ia tinggal lama di ingatan, mengganggu tidur, memengaruhi cara seseorang memandang diri dan dunia.
Negara sebenarnya sudah punya aturan. UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur banyak hal yang dulu sering dianggap sepele. Pelecehan verbal, sentuhan tanpa izin, pemaksaan perkawinan, sampai kekerasan seksual di ruang digital kini diakui sebagai kejahatan. Sayangnya, di lapangan, aturan ini sering kalah oleh budaya saling melindungi, rasa sungkan, dan ketakutan korban untuk bicara.
Konstitusi kita juga jelas. Setiap orang berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman. Namun kenyataannya, banyak perempuan justru merasa tidak aman di ruang yang seharusnya melindungi mereka. Rumah, sekolah, pesantren, bahkan kampus, berkali-kali muncul dalam daftar tempat terjadinya kekerasan seksual.
Data Komnas Perempuan tahun 2023 mencatat ratusan ribu kasus kekerasan terhadap perempuan. Angka itu besar, tapi yang lebih besar adalah jumlah korban yang memilih diam. Mereka diam karena takut disalahkan, takut tidak dipercaya, atau takut masa depannya hancur. Dalam banyak kasus, korban justru ditanya soal pakaian, sikap, atau jam pulang, sementara pelaku berlindung di balik jabatan dan nama baik.
Kasus pelecehan seksual di lingkungan pendidikan beberapa waktu terakhir menunjukkan satu hal penting: kekerasan seksual sering lahir dari relasi kuasa yang tidak sehat. Ketika seseorang merasa punya kendali atas orang lain, dan lingkungan membiarkannya, kekerasan mudah terjadi. Ini bukan soal moral semata, tapi soal sistem yang gagal melindungi yang lemah.
Dampaknya tidak ringan. Banyak perempuan mengalami gangguan kesehatan mental, kehilangan kepercayaan diri, bahkan kesulitan melanjutkan pendidikan atau pekerjaan. Kekerasan seksual sering mendorong korban masuk ke dalam lingkaran kemiskinan dan keterasingan sosial. Luka itu tidak selalu terlihat, tapi nyata dirasakan.
Saya percaya, pencegahan tidak cukup hanya dengan hukum dan hukuman. Edukasi tentang hak-hak perempuan, cara melapor yang aman, serta keberanian masyarakat untuk berpihak pada korban jauh lebih penting. Perempuan perlu tahu bahwa tubuh dan hidupnya bukan milik siapa pun selain dirinya sendiri.
Undang-Undang PKDRT, UU TPKS, dan komitmen Indonesia pada Konvensi CEDAW seharusnya menjadi alat, bukan pajangan. Hukum harus hadir untuk melindungi, bukan sekadar menenangkan opini publik.
Kekerasan seksual terhadap perempuan adalah kesalahan kita bersama jika terus dibiarkan. Selama korban masih dipaksa diam dan pelaku masih dilindungi, kejahatan ini akan terus berulang. Sudah waktunya kita berhenti menormalisasi luka, dan mulai serius melindungi manusia.