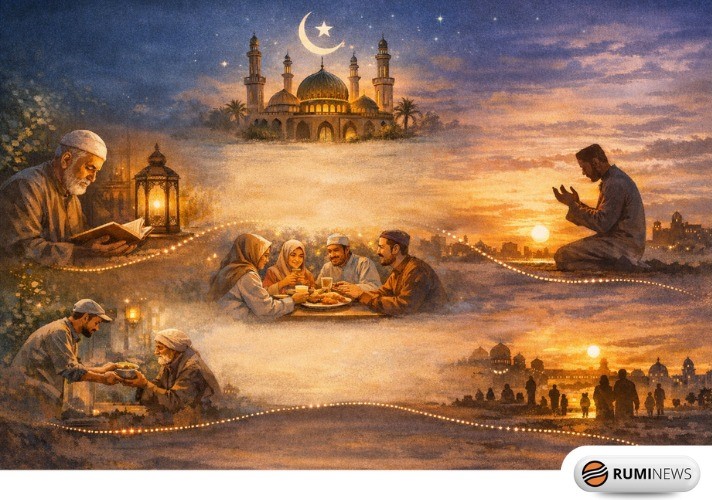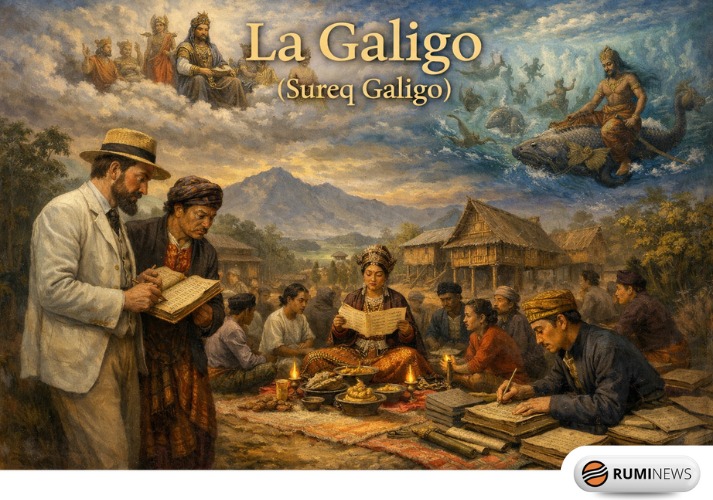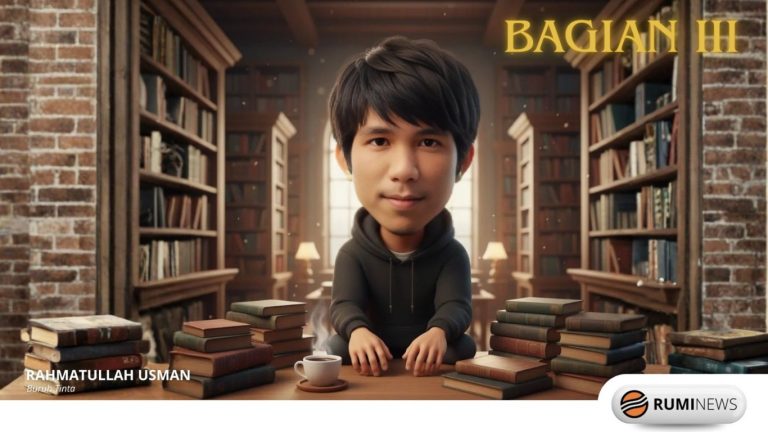ruminews.id – Sejak kita dilahirkan, kita sudah dibekali kemampuan alami untuk belajar. Belajar bukan sekadar aktivitas tambahan, melainkan bagian dari kodrat manusia. Bahkan seorang bayi yang baru lahir pun langsung memulai proses belajar: ia menangis bukan hanya karena refleks, tetapi juga sebagai cara pertama untuk berkomunikasi dengan lingkungan; ia tersenyum untuk menarik perhatian dan membangun hubungan; ia berulang kali jatuh bangun saat belajar berjalan. Semua ini menunjukkan bahwa kehidupan manusia sejak awal adalah perjalanan belajar tanpa henti.
Bukti ilmiah terbaru juga memperkuat pandangan ini. Sebuah penelitian yang diterbitkan di jurnal eLife pada tahun 2024 menemukan bahwa bayi baru lahir sudah memiliki kemampuan statistical learning, yaitu belajar mengenali pola-pola secara otomatis dari lingkungan. Tidak hanya terbatas pada bahasa, tetapi juga berlaku lintas bidang, yang berarti otak bayi sudah siap sejak awal untuk menyerap informasi secara luas. Penelitian ini menggunakan metode neuro-perilaku, termasuk pencatatan aktivitas otak (EEG), sehingga kesimpulannya sangat kuat secara ilmiah. Temuan ini menegaskan bahwa kemampuan belajar memang melekat pada kodrat manusia.
Selain itu, sebuah ulasan ilmiah di jurnal Trends in Neurosciences (2023) menjelaskan bahwa rasa ingin tahu (curiosity) adalah mekanisme saraf bawaan yang mendorong manusia untuk terus belajar. Artikel ini merangkum berbagai penelitian dengan pendekatan fMRI, rekaman aktivitas saraf, hingga model komputasi, dan menunjukkan bahwa dorongan ingin tahu mengaktifkan sistem saraf tertentu yang membuat kita terdorong menjelajah, mencari informasi, dan menemukan hal-hal baru. Dengan kata lain, bukan hanya kita bisa belajar, tetapi kita juga secara alami terdorong untuk belajar. Gabungan kedua temuan ini memperlihatkan gambaran yang selaras: manusia memang diciptakan untuk belajar sepanjang hidup. Sejak lahir kita sudah memiliki perangkat otak yang memungkinkan pembelajaran, dan rasa ingin tahu yang menuntun arah pembelajaran itu.
Sejak lahir, manusia memang sudah memiliki potensi dasar untuk merasakan emosi, semacam “benih” yang tertanam dalam diri kita. Namun, arah pertumbuhan emosi itu – apakah berkembang menjadi sesuatu yang konstruktif seperti kasih sayang, empati, dan syukur, atau justru destruktif seperti kebencian, iri, dan amarah berlebihan – ditentukan melalui proses belajar sepanjang hidup. Artinya, walaupun fondasi biologis untuk merasakan emosi sudah ada sejak bayi, kualitas dan bentuk emosinya dibentuk oleh pengalaman, lingkungan, dan kebiasaan yang terus-menerus kita jalani. Dengan kata lain, kodrat manusia adalah menjadi “makhluk pembelajar emosi”. Kita tidak dilahirkan langsung dengan kebencian yang matang atau kasih sayang yang mendalam. Yang ada hanyalah potensi dasar: seorang bayi bisa merasa tidak nyaman atau senang, tapi bagaimana rasa itu berkembang menjadi cinta yang hangat atau dendam yang pahit sangat bergantung pada pengalaman dan kesadaran yang kita tumbuhkan. Proses belajar inilah yang menjadikan emosi manusia kaya dan beragam
Kehidupan pada dasarnya dapat dipahami sebagai sebuah medan ujian. Setiap orang yang kita temui, setiap peristiwa yang kita alami, bahkan hal-hal kecil yang hadir dalam keseharian, sesungguhnya membawa peluang bagi kita untuk merespons dengan cara yang membangun jiwa atau justru merusaknya. Ketika kita memilih respons konstruktif – misalnya memaafkan kesalahan orang lain, bersyukur atas apa yang ada, menolong sesama, atau belajar dari kesulitan – maka jiwa kita tumbuh semakin kuat dan matang. Sebaliknya, ketika seseorang jatuh pada respons destruktif – seperti menyimpan dendam, merasa iri, tamak, atau berputus asa – maka jiwanya terhimpit dan semakin rapuh. Karena manusia memang diciptakan sebagai makhluk pembelajar, setiap situasi yang datang, baik manis maupun pahit, sebenarnya adalah pelajaran terbuka yang mengundang kita untuk naik tingkat kesadaran.
Sayangnya, dalam kenyataan sehari-hari banyak manusia justru lebih sering belajar dan membiasakan diri untuk merespons secara destruktif. Bukan karena sejak lahir kita sudah “ditakdirkan jahat”, melainkan karena pola hidup, lingkungan, dan pengalaman yang dialami seringkali menanamkan kebiasaan yang merusak jiwa. Ada orang yang terbiasa menyimpan dendam karena sejak kecil melihat kemarahan dipelihara di keluarganya; ada pula yang tumbuh dalam budaya persaingan tidak sehat sehingga mudah iri, tamak, atau merasa tidak pernah cukup. Lama-kelamaan, pola respons destruktif ini melekat sebagai kebiasaan, bahkan terasa wajar, padahal sebenarnya ia melemahkan hati dan menutup jalan pertumbuhan kesadaran.
Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan belajar manusia adalah pedang bermata dua: ia bisa membawa kita ke arah yang lebih luhur, tetapi juga bisa menyeret kita ke jurang kehancuran. Itulah sebabnya, bahkan untuk bisa bersyukur pun kita perlu belajar dan berlatih. Rasa syukur memang berakar pada potensi dasar emosi positif yang sudah ada dalam diri kita sejak lahir, namun ia tidak serta-merta hadir dalam bentuk yang matang. Seorang bayi bisa merasa nyaman ketika dipeluk atau diberi makan, tetapi kemampuan untuk menyadari makna kenyamanan itu sebagai sesuatu yang patut disyukuri baru terbentuk melalui pengalaman dan pembiasaan.
Dalam kehidupan sehari-hari, syukur bukanlah sekadar ucapan “terima kasih”, melainkan sebuah sikap batin yang melihat nilai dan kebaikan dalam setiap keadaan, termasuk di balik kesulitan. Untuk sampai pada tahap itu, dibutuhkan latihan: mulai dari menyadari hal-hal kecil yang bisa diapresiasi, membiasakan diri mencatat atau merenungkan nikmat yang diterima, hingga melatih pikiran agar tidak hanya fokus pada kekurangan. Neurosains pun menunjukkan bahwa latihan syukur secara konsisten dapat membentuk jalur saraf baru di otak yang membuat kita lebih mudah merasakan emosi konstruktif. Artinya, syukur benar-benar bisa dipelajari, ditumbuhkan, dan dikuatkan. Jadi, bersyukur bukan sekadar bawaan, tetapi sebuah keterampilan jiwa yang perlu diasah agar semakin alami dan menjadi bagian dari diri kita.
Rangkaian penelitian terkini menunjukkan bahwa bersyukur memang dapat dilatih, dan efeknya terbukti nyata meskipun dengan intensitas yang bervariasi. Studi internasional berskala besar, seperti meta-analisis yang melibatkan hampir 25.000 peserta dari 28 negara, menegaskan bahwa intervensi syukur konsisten memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan psikologis lintas budaya. Hasil ini diperkuat oleh berbagai penelitian eksperimental di jurnal bereputasi tinggi seperti BMC Women’s Health (2025), Current Psychology (2024), dan SAGE Journals (2023), yang menemukan bahwa praktik syukur – baik melalui jurnal, penulisan syukur, maupun pelatihan daring – mampu meningkatkan emosi konstruktif, mengurangi pikiran negatif yang berulang, memperkuat spiritualitas, hingga mendorong pertumbuhan pasca-trauma. Keseluruhan bukti ini menunjukkan bahwa syukur bukanlah sekadar perasaan spontan, melainkan keterampilan emosional yang bisa dilatih secara sadar. Dengan latihan rutin – menulis jurnal syukur, mengungkapkan rasa terima kasih, atau merenungkan hal-hal yang patut dihargai – manusia dapat memperkuat jalur saraf positif di otak, meningkatkan kesejahteraan mental, serta membentuk daya tahan emosional dalam menghadapi berbagai ujian kehidupan.