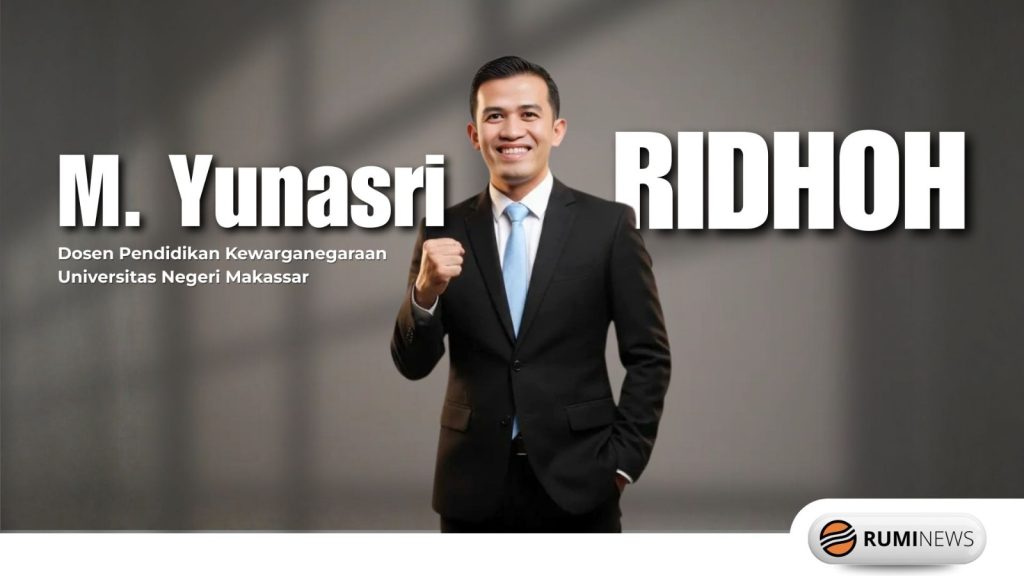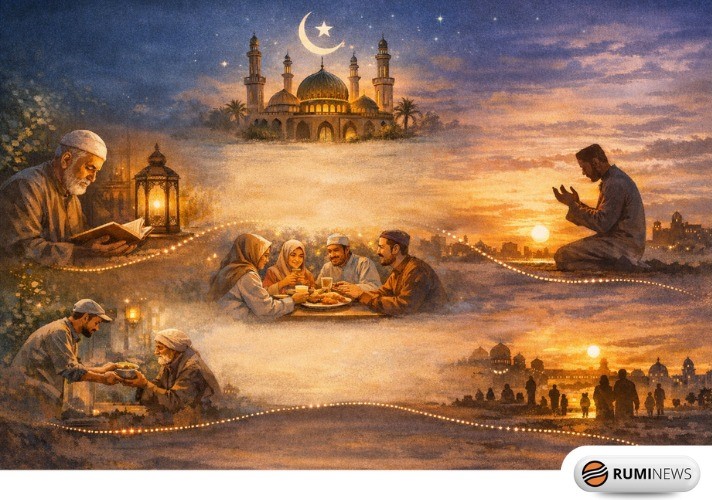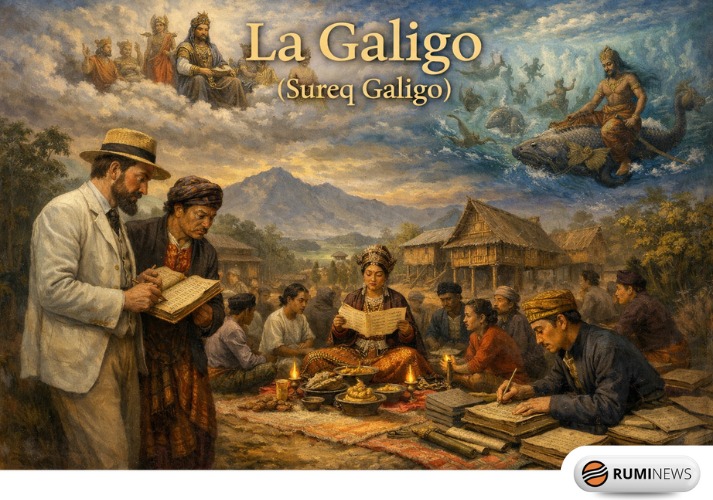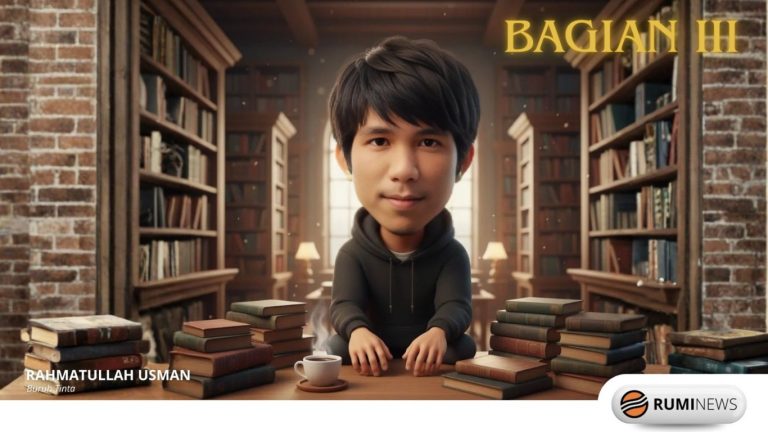ruminews.id – Pernahkah Anda mendengar status kewarganegaraan diperjualbelikan? Sebagaimana mendagangkan sepatu, kendaraan, daging, timah, atau saham perusahaan dan beragam dagangan lainnya. Faktanya saat ini kewarganegaraan pun bisa dibeli dan dijual. Saat ini banyak negara, tidak lagi menjadikan kewargaansekadar sebagai identitas politik dan kultural, tapi menjadi semacam komoditas ekonomi yang memiliki harga, nilai tukar, bahkan paket promosi.
Secara akademik fenomena ini dikenal dengan istilah “Citizenship by Investment” (CBI), di mana seseorang dapat memperoleh kewarganegaraan suatu negara dengan imbalan investasi tertentu.
Citizenship for Sale?
Praktik ini sebetulnya dan senyatanya sudah lamaberlangsung, sejak 1980 an, terutama di beberapa negara kecil yang menghadapi keterbatasan sumber daya, seperti Saint Kitts and Nevis, Dominika, dan Antigua & Barbuda, yang belakangan merambah Eropa dan Asia. Di Malta, misalnya, status kewarganegaraan dapat diperoleh dengan membayar sekitar 1 juta euro. Begitu juga di Vanuatu, kewarganegaraan dijual hanya dengan 130 ribu dolar AS.
Bagi negara penjual, ini disebut “strategi ekonomi baru” untuk menarik investasi. Namun bagi banyak akademisi dan pengamat politik, ini adalah tanda komodifikasi kewarganegaraan, di mana kewarganegaraan diperlakukan tidak lebih sekadar sebagai barang dagangan di pasar internasional.
Dalam literatur sosiologi kewarganegaraan, fenomena ini disebut “komodifikasi kewarganegaraan,” yaitu ketika status warga negara dilepaskan dari makna moral, loyalitas, dan kebersamaan politik, lalu dikonversi menjadi nilai ekonomi. Kewarganegaraan yang dulu dipandang sebagai hubungan timbal balik antara wargadan negara, di mana hak untuk dilindungi dan kewajiban untuk berkontribusi, kini ditransformasikan menjadi aset pribadi.
Ayelet Shachar dalam artikelnya “Citizenship for Sale?” (2017) menggambarkan kondisi ini sebagai bentuk “privatisasi hak politik.” Negara tidak lagi menjadi penjaga kedaulatan moral, melainkan agen penjual status hukum. Di tangan birokrasi global, paspor menjadi simbol mobilitas dan kekuasaan ekonomi. Orang kaya membeli paspor bukan karena ingin menjadi bagian dari komunitas politik dan berkontribusi untuknya, tetapi karena ingin memiliki visa-free accesske lebih banyak negara, menghindari pajak, atau mengamankan masa depan di tengah ketidakpastian geopolitik.
Dengan kata lain, kewarganegaraan menjadi semacam “asuransi global bagi kaum superkaya.” Kondisi ini mengafirmasi terjadinya marketization of citizenship,semacam pasar global yang memperdagangkan sipil politik (sipol) dan ekonomi, sosial, budaya (ekosob)secara legal. Rainer Baubock (2018) menyebut ini sebagai commodification of citizenship, yaitu proses ketika kewarganegaraan menjadi barang dagangan yang diobral ke penduduk dunia.
Solidaritas No, Komoditas Yes
Tak berhenti di sana, Kristin Surak (2023) dalam bukunya The Golden Passport: Global Mobility for Millionaires menyebut munculnya fenomena baru yang disebut citizenship industry, sebuah industri global yang memperjualbelikan status politik manusia dengan mekanisme pasar. Ada agen internasional, konsultan hukum, dan lembaga keuangan yang menyediakan jasa pengurusan “paspor premium” lengkap dengan katalog produk dan keunggulan tiap negara. Negara menjadi penjual, sementara warga dunia berduit menjadi pembeli, dan diantaranya ada broker investasi.
Industri ini diatur seperti industri pariwisata atau real estat. Ada daftar harga, proses aplikasi, hingga paket promosi “fast-track citizenship.” Negara-negara kecil di Karibia memanfaatkan skema ini untuk meningkatkan pendapatan nasional. Namun dalam perspektif politik global, hal ini memperlihatkan neoliberalisasi kedaulatan, di mana negara memperlakukan kewarganegaraan sebagai instrumen ekonomi, bukan sebagai simbol keanggotaan kolektif.
Bagi banyak negara berkembang yang menghadapi defisit fiskal, program ini tampak menguntungkan. Namun di sisi lain, ia menimbulkan problem ketimpangan moral yang serius. Paspor, yang dulu menjadi hasil perjuangan kolektif rakyat dalam membangun negara, kini dapat dimiliki siapa pun yang mampu membayarnya, tanpa pernah berkontribusi sosial, budaya, atau politik.
Pertanyaan yang kemudian muncul adalah, apakah kewarganegaraan masih memiliki makna moral-kultural? Ataukah ia telah berubah menjadi simbol status ekonomi semata? Dalam kerangka pemikiran klasik, seperti yang diungkapkan oleh T.H. Marshall (1950), kewarganegaraan merupakan kombinasi dari tiga dimensi hak: sipil, politik, dan sosial. Ketiganya berfungsi menjaga keseimbangan antara warga dan negara.
Namun, dalam konteks perdagangan kewarganegaraan, hak-hak tersebut tidak lagi diperoleh melalui partisipasi atau identitas, melainkan melalui transaksi ekonomi. Inilah yang disebut Shachar dan Bauböck (2018) sebagai “depolitisasi kewarganegaraan.” Ketika pasar mengambil alih ruang moral politik, maka hak dan identitas warga tidak lagi berakar pada solidaritas, melainkan pada kapital.
Kini kita menyaksikan paradoks baru, yakni di satu sisi, jutaan orang di dunia mengungsi karena kehilangan kewarganegaraan, atau sering disebut stateless citizensyang tidak diakui oleh negara mana pun, mereka bertaruh nyawa berlayar di lautan untuk mencari suaka. Di sisi lain, segelintir orang bisa membeli kewarganegaraan ganda dengan mudah. Kewarganegaraan, yang dulu menjadi wajah kesetiaan dan kebangsaan, kini menjadi alat eksklusivitas dan mobilitas global.
Zygmunt Bauman pernah menggambarkan dunia ini sebagai masyarakat cair (liquid society). Dimana, dalam dunia yang cair, orang-orang kaya mengalir bebasmelintasi berbagai negara, sementara yang miskin mengendap dan terperangkap, menjalani hari dalam ketakutan, kemelaratan dan berbagai ketidakadilan.
Sakralitas Warga dan Bangsa
Fenomena perdagangan kewarganegaraan menggambarkan pergeseran besar dalam cara kita memandang konsep “warga” dan “bangsa.” Jika dahulu nasionalisme menjadi dasar bagi pembentukan negara modern, kini logika pasar global mulai menggerus batas-batas tersebut. Negara yang dulu menjadi rumah bagi warga kini berubah menjadi perusahaan penyedia jasa hukum.
Dari perspektif etika politik, fenomena ini memunculkan paradoks. Kewarganegaraan sejatinya merupakan merupakan bentuk tertinggi keterikatan politik. Dalam pandangan klasik Aristoteles, warga adalah zoon politicon, makhluk politik yang aktif dan bertanggungjawab dalam urusan publik. Namun dalam logika citizenship by investment, keterikatan itu menjadi pasif dan transaksional.
Dalam pandangan ini, keputusan negara untuk menjual kewarganegaraan bukan hanya persoalan kebijakan, tetapi juga persoalan moral publik. Ketika kewarganegaraan dijual kepada investor asing, maka nilai solidaritas antarwarga menjadi terdistorsi. Kewarganegaraan kehilangan fungsi profetik dan egaliternya.
Indonesia, dengan sistem hukumnya sebetulnya tidak mengenal konsep jual beli kewarganegaran. Undang-undang 12 tahun 2006 menegaskan bahwa kewarganegaraan hanya dapat diperoleh melalui kelahiran, perkawinan, atau naturalisasi dengan syarat tertentu (tinggal di Indonesia dalam jangka waktu tertentu, berbahasa Indonesia, mengakui Pancasila dan UUD 1945, serta tidak memiliki kewarganegaraan ganda).
Namun demikian, meski Indonesia belum menerapkan program Citizenship by Investment, namun ada gejalayang patut diwaspadai dan dievaluasi, yakni gejala dalam praktik pemberian izin tinggal terbatas, visa investasi, atau bahkan naturalisasi istimewa bagi atlet dan tokoh tertentu. Walaupun konteksnya berbeda, logika yang bekerja tetap sama, yakni hak kewarganegaraan diberikan atas dasar nilai ekonomi, bukan nilai kebangsaan.
Jika tidak dikawal dengan baik, praktik ini berpotensi mengikis makna kebangsaan yang telah lama dibangun. Di tengah krisis moral publik dan politik uang, membuka ruang bagi komersialisasi kewarganegaraan hanya akan memperparah ketimpangan sosial dan melemahkan solidaritas nasional.
Kewarganegaraan seharusnya tidak dijadikan barang dagangan, sebab ia adalah kontrak sosial yang mendasari keberadaan sebuah bangsa. Ia bukan hanya hak untuk memiliki paspor, tetapi juga tanggung jawab untuk berkontribusi, berpartisipasi, dan menjaga nilai-nilai konstitusi.
Dalam dunia yang kian terfragmentasi oleh uang dan status, mempertahankan makna kewarganegaraan adalah perjuangan moral yang mendesak. Apalagi di tengah dunia yang semakin terhubung dan terbuka, memang sulit menolak logika pasar global. Namun negara tetap harus menjadi penjaga moral publik. Menjual kewarganegaraan sama artinya dengan menjual identitas kebangsaan, yang bisa melemahkan legitimasi negara, dan mengancam kesetaraan warga.
Kita perlu kembali pada semangat dasar bahwa menjadi warga negara bukan sekadar soal status hukum, tetapi soal rasa memiliki, partisipasi, dan tanggung jawab kolektif. Di sinilah letak pentingnya pendidikan kewarganegaraan, untuk menanamkan kembali makna luhur menjadi warga yang bukan dibeli, melainkan dibangun bersama.